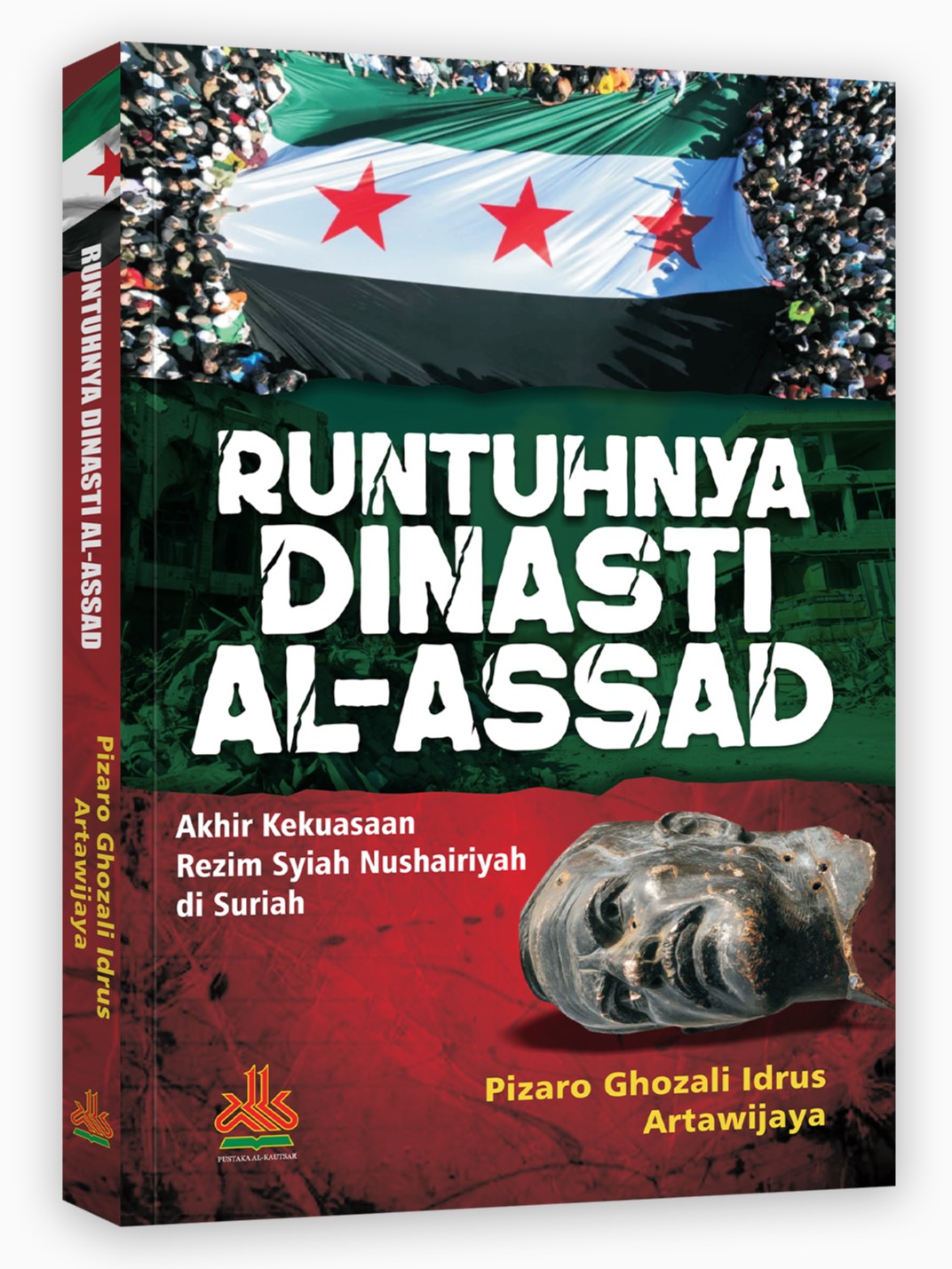Pemerintah Amerika Serikat (AS) tampaknya kini semakin memahami permainan politik Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Menurut analis politik harian Maariv, Ran Adelist, Washington sadar bahwa Netanyahu tengah berupaya memicu kembali konfrontasi militer dengan Hamas.
Bukan karena alasan keamanan atau strategi nasional, melainkan untuk menghindari tekanan hukum dan politik yang kian menjeratnya di dalam negeri.
Adelist menulis bahwa langkah ini dilakukan Netanyahu di tengah upaya internasional yang digerakkan AS dan mitra-mitranya di kawasan untuk “menduniakan” persoalan Palestina-Israel.
Sebuah arah politik baru yang bertujuan membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih permanen.
Manuverlama Netanyahu
Menurut Adelist, utusan Presiden AS Donald Trump, Steven Witkoff, bersama penasihat senior Jared Kushner, telah menangkap dengan jelas satu-satunya celah yang masih bisa dimanfaatkan Netanyahu untuk menghentikan proses perdamaian yang disepakati di Sharm el-Sheikh, Mesir.
Caranya, dengan menuduh Hamas melanggar gencatan senjata—sebuah dalih untuk kembali melancarkan serangan militer.
“Netanyahu menginginkan perang, dan pihak Amerika tahu betul alasannya, Ia ingin lolos dari proses peradilannya sendiri,” tulis Adelist.
Washington, lanjutnya, memandang tuduhan Netanyahu bahwa Hamas menunda pengembalian jenazah tentara Israel hanyalah alat politik domestic.
Sebuah upaya membangkitkan emosi publik dan menyiapkan pembenaran untuk menyalakan kembali front pertempuran.
Padahal, kata Adelist, langkah itu justru mengabaikan gambaran besar yang sedang diupayakan pemerintahan Trump.
Sebuah proyek penyelesaian komprehensif yang berpotensi membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina dengan dukungan internasional yang luas.
Antara tekanan dan ketidakpercayaan
Kedatangan Kushner dan Witkoff ke Israel awal pekan ini, menurut Adelist, menyerupai “kunjungan utusan mafia kepada pedagang sayur yang menolak membayar upeti”.
Sindiran atas tekanan keras yang mereka lakukan agar Netanyahu tetap berada di jalur perdamaian yang diatur Washington.
Tak lama setelah keduanya, Wakil Presiden AS J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga datang untuk memantau sejauh mana Israel mematuhi kesepakatan tersebut.
Namun, ujar Adelist, Netanyahu dan mitra politiknya bersikeras berpura-pura bahwa “perjanjian Sharm el-Sheikh telah mati sejak hari pertama”.
Faktanya, di balik layar, koordinasi langsung antara militer Israel dan Pentagon tengah berlangsung aktif. Adelist menilai bahwa tujuan militer kini tidak lagi sejalan dengan ambisi politik Netanyahu.
“Konferensi Sharm el-Sheikh pada dasarnya merupakan deklarasi tidak resmi dari upaya internasional untuk menyingkirkan Netanyahu dan kelompoknya dari rancangan tatanan baru di Timur Tengah,” tulisnya.
Hamas tetap ada, arah baru menuju negara Palestina
Adelist juga menyinggung keterlibatan langsung sejumlah kekuatan asing yang menuju Gaza.
Menurutnya, mereka “tidak datang untuk berperang dengan Hamas, melainkan memastikan Israel tidak lagi menyerang Gaza.”
Pengelolaan wilayah Gaza, menurut skenario yang ia paparkan, akan diserahkan kepada “pemerintahan teknokrat” yang fokus pada rekonstruksi, dengan Tony Blair disiapkan sebagai koordinator internasional.
“Ini akan menjadi ujian berat bagi pemerintahan Smotrich,” tulis Adelist, “karena Blair dikenal mendukung pembentukan negara Palestina.”
Namun, ia mengingatkan, proses ini sangat rapuh.
“Pertanyaan yang menggelisahkan adalah: apa yang bisa runtuh? Jawabannya: segalanya,” katanya.
Adelist mengutip sejumlah pernyataan dari peserta konferensi Sharm el-Sheikh.
Termasuk jurnalis CNN Clarissa Ward yang menyebut forum itu “sebagai langkah pembuka menuju negara Palestina”, serta mantan perdana menteri Ehud Barak yang menilai “dokumen Trump memiliki momentum nyata ke arah itu.”
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pun, menurutnya, menegaskan perlunya “menjaga momentum tersebut”.
Koordinasi baru di lapangan
Menurut Adelist, penyebaran pasukan asing di Gaza akan menjadi indikator sejauh mana proses ini serius.
Tujuan utamanya, katanya, adalah “mencegah Israel kembali menguasai Gaza”.
Pernyataan Trump tentang “kembali berperang dengan kekuatan penuh” disebutnya hanya retorika politik belaka.
Ia mengakui bahwa tuntutan Israel untuk mengembalikan jenazah tentaranya adalah hal yang sah.
Namun, ia menolak logika bahwa hal itu menjadi alasan cukup untuk menyalakan kembali perang.
“Apakah pantas mengorbankan tentara yang hidup demi jenazah? Jawabannya: tidak,” tegasnya.
Menurutnya, Hamas sendiri juga berkepentingan menjaga ketenangan. Gerakan itu ingin berperan dalam upaya rekonstruksi Gaza dan memperkuat posisi politiknya di Tepi Barat.
Adelist mengutip hasil riset lembaga Tamar yang dipimpin peneliti Shaul Arieli, yang menunjukkan bahwa 43 persen warga Tepi Barat menolak pelucutan senjata Hamas dan mendukung pemerintahan gabungan Fatah–Hamas.
“Angka ini menunjukkan realitas baru yang harus dihadapi Israel. Kepentingan keamanan sejati Israel justru terletak pada masa tenang yang cukup panjang untuk membangun kembali kekuatan militernya—bukan pada perang demi mempertahankan kekuasaan politik,” tulisnya.
Realitas internal Israel
Pada bagian akhir tulisannya, Adelist menyoroti kondisi politik domestik Israel. Rencana pengesahan undang-undang pembebasan wajib militer, katanya, akan memperparah krisis di tubuh militer.
Ia mendesak Kepala Staf Angkatan Darat, Eyal Zamir, untuk “bersikap sebagai negarawan sejati” dan bekerja sama dengan militer AS dalam melaksanakan hasil kesepakatan Sharm el-Sheikh.
Ia menilai pemerintah Netanyahu hidup dalam “dunia khayal” dengan wacana membuka jalur darat ke Daraa untuk membantu komunitas Druze, serta desakan agar Hizbullah dilucuti yang “secara praktis berarti memicu perang saudara di Lebanon.”
“Ini adalah hasil dari kebijakan kanan yang bodoh dan kehilangan arah,” katanya.
Ia menyarankan Israel menjaga hubungan hati-hati dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mencapai gencatan senjata stabil dengan Suriah, dan berhenti menebar ancaman terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin.
“Memiliki senjata tidak berarti akan menggunakannya. Senjata adalah alat pencegah, bukan pemicu perang bagi mereka yang tidak menginginkannya,” tulisnya.
Menutup tulisannya, Adelist mengajukan pertanyaan.
“Kapan dan berapa banyak pasukan asing yang akan masuk ke Gaza, bagaimana mereka akan berkoordinasi dengan Hamas, dan bagaimana reaksi pemerintah Israel yang histeris?” tanyanya.
Menurutnya, militer Israel sudah lebih dahulu menjalankan kesepakatan Sharm el-Sheikh bersama Pentagon, sementara Netanyahu dan Menteri Pertahanannya hanya berpura-pura memberi perintah.
“Sebab jika mereka mengakuinya,” tulis Adelist, “maka karier politik mereka akan tamat di pemilu berikutnya.”