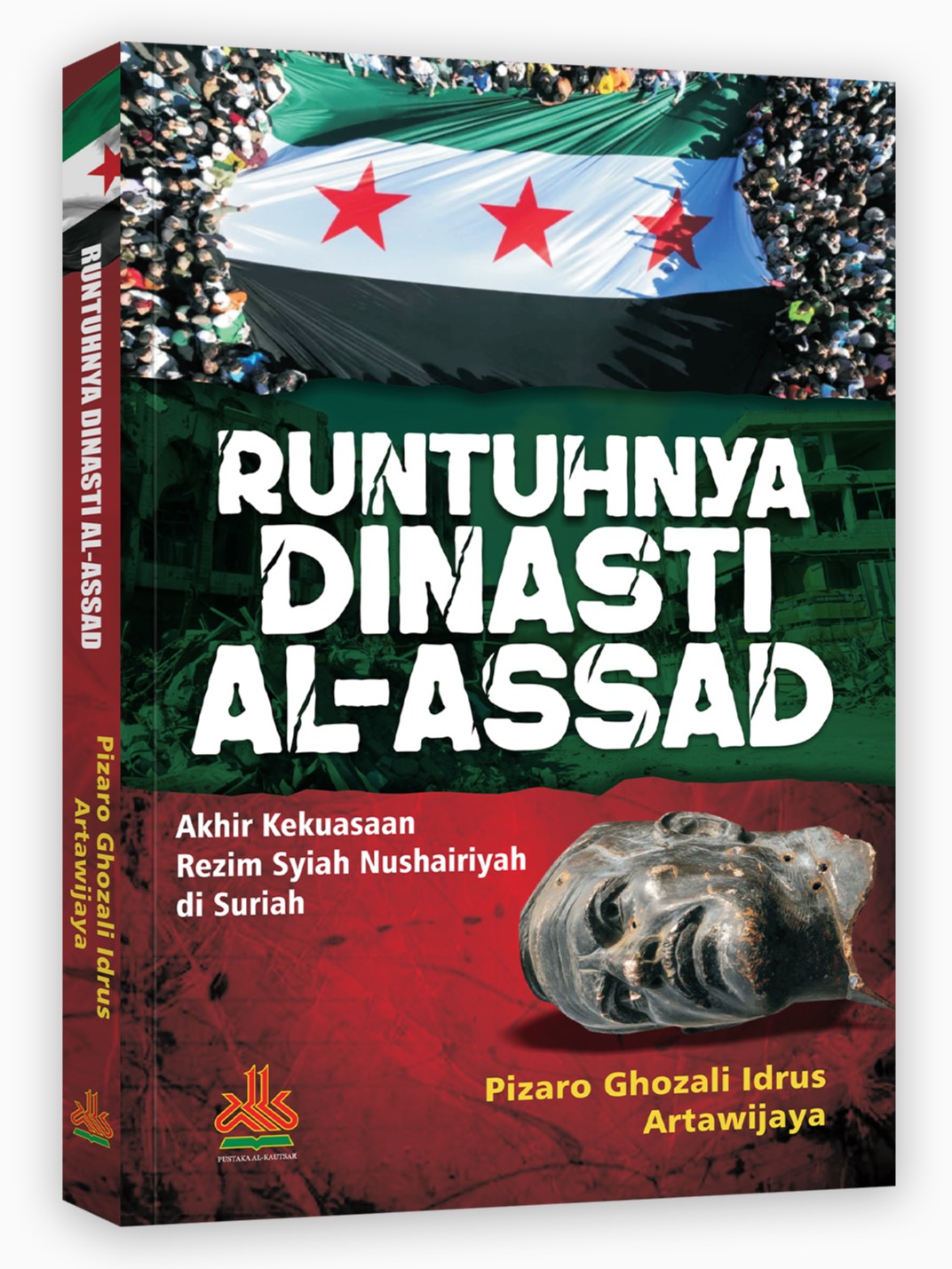Serangan dan pembunuhan yang terus meningkat oleh Israel di Jalur Gaza tidak lagi bisa dianggap sekadar pelanggaran terhadap gencatan senjata.
Menurut sejumlah analis, tindakan tersebut telah menjadi pola yang sistematis—menunjukkan bahwa perang sebenarnya masih berlanjut di bawah payung “rencana perdamaian” Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Pada Rabu malam, Israel menewaskan dua warga Palestina di lingkungan As-Salathin, Gaza Utara, hanya beberapa jam setelah mengumumkan kembali ke status gencatan senjata.
Sebelumnya, pada Selasa malam, serangan udara besar-besaran menewaskan 104 warga Palestina dan melukai 153 lainnya.
Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa pasukannya tengah beroperasi di wilayah jaringan terowongan di Kota Khan Younis, Gaza Selatan.
Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Washington “terus memantau situasi dari dekat” dan akan mengirim delegasi ke Israel.
Namun, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian tersebut dan menyerukan kepada para mediator untuk menekan Tel Aviv agar menghormati komitmennya.
Presiden Trump, sebaliknya, menyatakan pada Selasa bahwa Israel tidak melanggar kesepakatan, dan bahwa tindakan militernya merupakan bentuk pembelaan diri.
Ia juga memperingatkan Hamas agar “berperilaku baik” jika tidak ingin “dihapuskan dari muka bumi”.
Amerika Serikat jauh dari realitas lapangan
Sikap Washington, menurut sejumlah pengamat, menunjukkan betapa pemerintahan Trump sama sekali tidak berhadapan dengan kenyataan di lapangan.
Selain itu juga menelan mentah-mentah narasi Israel untuk membenarkan pembunuhan warga Palestina yang kini menghadapi pembunuhan massal dan eksekusi di tempat.
“Perang sebenarnya masih terus berlangsung di Gaza, hanya saja kali ini terjadi di bawah naungan gencatan senjata,” ujar Dalia Arikat, dosen diplomasi dan penyelesaian konflik di Universitas Arab Amerika, dalam program Masar al-Ahdath (Lintasan Peristiwa).
Arikat menilai, kunjungan berulang para pejabat Amerika ke Israel tanpa menengok langsung ke wilayah pendudukan menunjukkan bias yang mendalam.
“Jika Trump sungguh ingin memainkan peran sebagai tokoh perdamaian seperti yang ia klaim, maka ia perlu datang ke Palestina—bukan sekadar berbicara tentang pembebasan tawanan Israel,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat, bersama Mesir, Qatar, dan Turki—yang ikut menandatangani kesepakatan—harus memantau pelaksanaan di lapangan dan memastikan kedua pihak mematuhinya.
Tanpa mekanisme pengawasan seperti itu, kata Arikat, Israel akan terus memberlakukan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina di bawah kedok gencatan senjata yang sejatinya tidak ada.
Lebih jauh, Arikat menyoroti sikap Washington yang hanya peduli terhadap jasad tawanan Israel.
Sementara “mengabaikan ratusan jenazah warga Palestina yang telah ditahan Israel selama bertahun-tahun”—suatu kebijakan yang ia sebut “kejahatan yang terencana dan sistematis”.
“Tidak bisa diterima bahwa lebih dari seratus warga Palestina—termasuk 46 anak-anak dan 20 perempuan—dibunuh, dan seluruh blok perumahan dihancurkan hanya untuk membalas kematian seorang tentara Israel, tanpa bukti apa pun bahwa warga Palestina berada di balik peristiwa itu,” kata Arikat mengutip pernyataan pakar urusan Israel, Dr. Mahmoud Yazbek.
Trump dinilai bertanggung jawab
Dr. Mahmoud Yazbek menilai, ini bukan kali pertama Israel menuduh perlawanan Palestina bertanggung jawab atas kematian tentaranya tanpa bukti. Sebelumnya, tuduhan serupa muncul di Rafah—daerah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Israel.
Yang menarik, kata Yazbek, adalah bagaimana Trump kali ini langsung mengadopsi versi Israel, bahwa “seorang pejuang keluar dari terowongan dan menembak seorang tentara”.
Padahal, pekan lalu Trump menolak narasi yang sama dan mengatakan “tidak bisa menuduh pihak Palestina tanpa bukti yang jelas”.
“Meski tentara itu telah dimakamkan, tidak ada bukti satu pun yang menunjukkan keterlibatan warga Palestina,” ujar Yazbek.
Ia menilai, reaksi Israel yang berlebihan menunjukkan paradoks besar kekuatan militer paling mematikan di dunia ternyata dipegang oleh tentara yang lemah—yang bahkan tak mampu melindungi dirinya di wilayah yang ia duduki sepenuhnya.
Bagi Yazbek, bahkan jika target serangan Israel adalah 7 atau 8 pemimpin Hamas seperti yang diklaim, pembunuhan massal terhadap warga di sekitar mereka “tidak lain hanyalah upaya untuk menyenangkan Benjamin Netanyahu yang sedang dilanda kemarahan.”
“Netanyahu, yang kini menghadapi ancaman dari Mahkamah Pidana Internasional, ingin tampil sebagai sosok kuat. Padahal semua orang tahu ia berada dalam posisi lemah, dan kini menumpahkan kelemahannya itu kepada warga Palestina yang tak bersenjata,” ujar Yazbek.
Ia menambahkan, tanggung jawab utama atas besarnya korban jiwa ada pada Presiden Trump.
Sebab, katanya, ia gagal memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan justru memberi lampu hijau kepada Israel untuk melakukan pembalasan tanpa pemeriksaan apa pun.
Upaya sistematis untuk menggagalkan kesepakatan
Ibrahim al-Madhoun, Direktur Lembaga Media Palestina, menilai bahwa Israel terus mencari-cari alasan untuk merusak kesepakatan, sementara Amerika Serikat dan para mediator lainnya memilih diam.
“Israel menggunakan dalih yang tidak bisa diverifikasi untuk membenarkan pembunuhan dan penghancuran rumah-rumah warga, sementara AS memberinya ruang untuk menetapkan aturan pertempuran baru,” ujar al-Madhoun.
Ia menilai, hal itu akan membuat kesepakatan berhenti di tahap awal tanpa pernah berkembang ke fase-fase berikutnya—yang berarti kegagalan total perjanjian.
Menurutnya, pembunuhan dan kehancuran besar-besaran di Gaza tak bisa dianggap sebagai respons atas kematian seorang tentara, bahkan sekalipun versi Israel itu benar.
“Jika para mediator tidak mengambil sikap tegas terhadap pola ini, maka perjanjian itu akan runtuh,” katanya.
Al-Madhoun menambahkan, Netanyahu tengah berusaha melarikan diri dari krisis politik dalam negerinya dengan menumpahkan amarah pada rakyat Palestina.
Ia juga menolak secara praktis melanjutkan kesepakatan setelah gagal meyakinkan Trump agar perang diteruskan—perang yang menurut al-Madhoun “belum pernah benar-benar berhenti”.
Di sisi lain, Thomas Warrick, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, menyebut tindakan Israel sepenuhnya “terkoordinasi dengan Washington.”
Amerika, katanya, mendukung “hak Israel untuk membela diri dan merespons setiap serangan tanpa harus kembali ke kondisi perang penuh.”
Menurut Warrick, Israel memang telah menyiapkan daftar target yang akan diserang secara cepat bila mendapat serangan dari Hamas—dan semuanya dilakukan dalam koordinasi dengan AS.
Ia juga menuding Hamas bertanggung jawab atas korban sipil, karena “para pemimpinnya tinggal di tengah masyarakat dan tidak memisahkan kombatan dari warga sipil.”
Meski mengakui sulit untuk memastikan pihak mana yang pertama menyerang pasukan Israel, Warrick menyatakan bahwa “Tel Aviv memandang Hamas sebagai pihak pelanggar perjanjian, dan bertindak berdasarkan anggapan itu.”