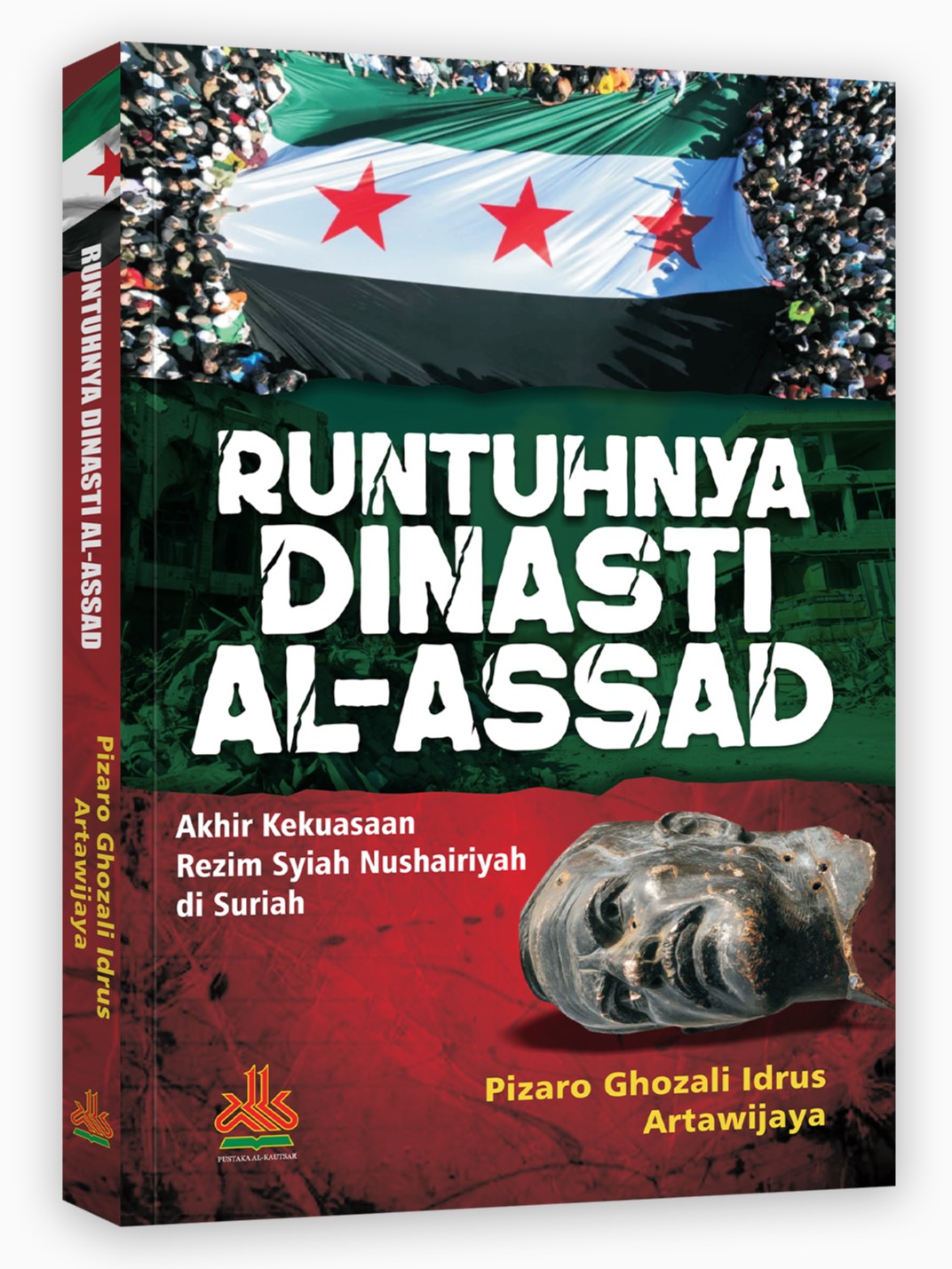Kunjungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Dan Keene, ke Tel Aviv dan penerbangannya dengan helikopter di atas Jalur Gaza menandai fase baru dalam keterlibatan Washington di wilayah itu.
Sejumlah analis menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan Amerika Serikat (AS) untuk memasuki tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza, sekaligus menegaskan siapa sebenarnya yang kini memegang kendali atas arah kebijakan pascaperang.
Menetapkan kendali dan arah baru
Menurut laporan media Israel, Keene bertemu dengan Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, pada Sabtu (1/11), dan bersama sejumlah pejabat tinggi kedua negara membahas koordinasi keamanan, masa depan pemerintahan sipil di Gaza, serta rencana rekonstruksi wilayah itu.
Sumber di pemerintahan AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Keene akan menyerahkan laporan lengkap kepada Presiden Donald Trump, Menteri Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional mengenai pelaksanaan gencatan senjata dan transisi menuju pemerintahan sipil di Gaza.
Dr. Mahmoud Yazbek, pakar urusan Israel, menilai kunjungan ini menjadi momen penting untuk “menetapkan garis besar peran Amerika di Gaza.”
Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mencoba memberi kesan bahwa Pusat Koordinasi Sipil-Militer yang baru dibuka di kota Kiryat Gat berada di bawah kendali Israel.
Namun, menurut Yazbek, kedatangan Keene justru memperlihatkan bahwa keputusan strategis terkait Gaza kini “sepenuhnya di tangan Amerika”—termasuk serangan udara yang dilakukan Israel pekan lalu.
Bagi Yazbek, pesan dari Washington jelas. AS ingin memastikan tahap kedua dari kesepakatan berjalan, meski Netanyahu berupaya menunda pelaksanaannya setidaknya hingga selesai pemilihan internal Partai Likud.
Amerika Tak ingin ulangi Irak dan Afganistan
Bagi mantan penasihat keamanan nasional AS, Mark Pfeifle, penerbangan Keene di atas Gaza menunjukkan keinginan Washington untuk “melihat langsung kondisi di lapangan”.
Selain itu juga memastikan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan mandatnya bersama mitra internasional seperti Mesir, Qatar, dan Inggris.
“Amerika Serikat tidak ingin pergi sendirian seperti di Irak atau Afganistan. Kali ini Washington ingin membangun kemitraan nyata di kawasan agar tak terjebak dalam perang panjang tanpa hasil,” kata Pfeifle.
Menurutnya, ketika rencana perdamaian Presiden Trump ditawarkan kepada negara-negara Arab dan disetujui secara prinsip, sudah disadari bahwa akan tiba waktunya bagi mereka untuk berpartisipasi secara finansial, militer, dan politik.
Kunjungan Keene, kata Pfeifle, adalah langkah politik yang bertujuan “menjembatani tantangan besar menuju stabilitas pascaperang” melalui kerja sama dengan Israel dan mitra regional.
Namun, Pfeifle menekankan bahwa agar kekuatan internasional yang akan ditempatkan di Gaza dapat berfungsi efektif, diperlukan mandat dan legitimasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tanpa payung PBB, negara-negara kawasan akan enggan terlibat,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan oleh Dalia Al-Areeqat, guru besar diplomasi dan penyelesaian konflik di Universitas Arab Amerika.
Menurutnya, pasukan internasional yang direncanakan harus berada di bawah mandat PBB dengan batasan yang jelas mengenai wilayah operasi dan kewenangannya.
“Yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah perlindungan internasional sejati dari dominasi militer Israel. Bukan pasukan penjaga perdamaian yang justru memberi ruang bagi Israel untuk terus melanggar hukum internasional,” kata Al-Areeqat.
Ia juga menyerukan agar mandat kekuatan itu diperluas untuk melindungi warga Palestina di Tepi Barat, mengingat pelanggaran dan kekerasan pemukim terus meningkat.
Yang paling penting, menurutnya, adalah memastikan kehadiran pasukan internasional menjadi jalan bagi penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza dan jaminan perlindungan hak-hak historis rakyat Palestina.
Analis politik Palestina, Iyad Al-Qarra, menilai posisi Amerika menunjukkan perubahan arah yang lebih positif dibanding sebelumnya.
Namun, ia menekankan bahwa langkah terpenting kini adalah memastikan implementasi nyata tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata.
Yakni penghentian pelanggaran Israel dan komitmen penuh terhadap perjanjian yang telah ditandatangani.
“Israel masih menghancurkan kawasan yang disebut zona kuning dan berusaha menghapusnya sepenuhnya untuk memperluas pendudukannya. Kekuatan internasional yang direncanakan tidak boleh menjadi payung untuk menutupi kejahatan semacam itu,” kata Al-Qarra.
Ia memperingatkan agar pasukan tersebut tidak berubah menjadi alat untuk membagi Gaza menjadi wilayah yang “dibangun kembali” dan wilayah yang dibiarkan hancur.
“Kalau Amerika benar-benar menginginkan perdamaian dan penghentian perang, maka tanggung jawab moral dan politik ada di tangan mereka,” ujarnya.
Menurut Al-Qarra, pernyataan terbaru Hamas bahwa mereka tidak berniat menjadi bagian dari pemerintahan Gaza pascaperang bisa menjadi landasan penting bagi rekonsiliasi nasional.
Ia menilai posisi itu membuka ruang bagi perundingan jangka panjang menuju gencatan senjata permanen dan tatanan sipil yang lebih stabil di Gaza.