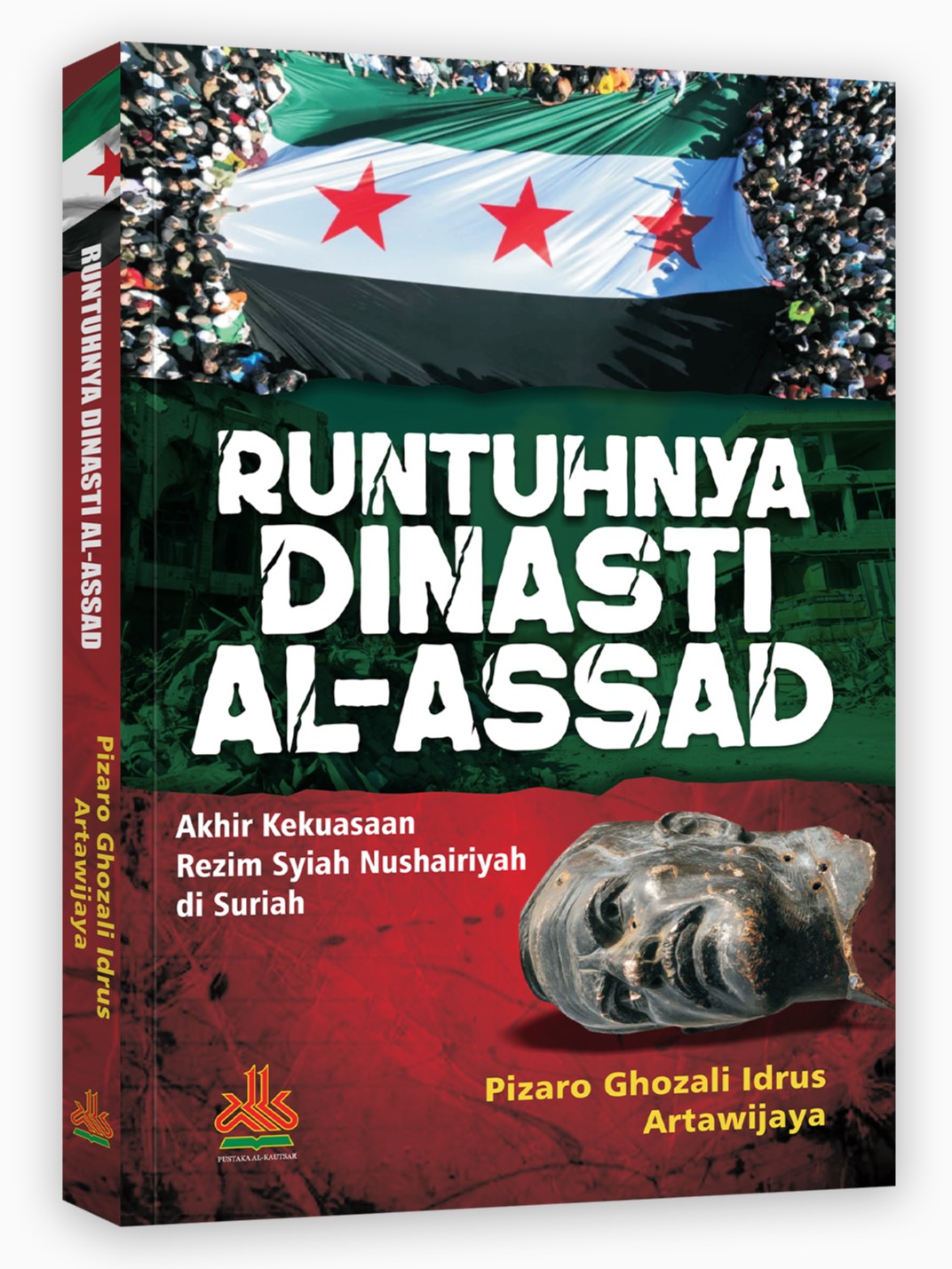Jauh sebelum negara Israel berdiri, para pemikir Zionis sudah menandai apa yang mereka sebut sebagai “masalah demografis” di tanah yang mereka incar.
Sejak akhir abad ke-19, persoalan jumlah penduduk non-Yahudi dipandang sebagai hambatan utama bagi kelangsungan negara yang direncanakan.
David Ben-Gurion, yang kelak menjadi perdana menteri pertama Israel, menegaskan hal itu secara gamblang pada 1947.
“Tidak mungkin ada negara Yahudi yang stabil dan kuat selama mayoritas penduduknya tidak melampaui 60 persen,” katanya.
Lebih jauh ke belakang, Theodor Herzl—pendiri gerakan Zionis—menulis dalam buku hariannya pada 1895:
“Kita akan berusaha mengusir penduduk miskin melintasi perbatasan tanpa menarik perhatian siapa pun.”
Maka, bagi Ben-Gurion pada 1948, persoalannya bukan lagi soal luas tanah yang harus direbut, melainkan nasib bangsa Palestina yang masih tinggal di atas tanah itu.
Sejarawan Israel, Ilan Pappé, dalam bukunya The Ethnic Cleansing of Palestine, menggambarkan gagasan inti dari proyek Zionis: membangun sebuah “benteng putih” di tengah dunia “gelap” Arab.
Dari situlah lahir ketakutan mendalam terhadap apa yang disebut hak untuk kembali—karena jika jutaan pengungsi Palestina kembali, keseimbangan demografis yang diidamkan Israel akan hancur.
Sepanjang puluhan tahun usia negara pendudukan itu, meskipun fokus kebijakannya bergeser ke arah penguatan militer, penguasaan nuklir, dan ketergantungan pada dukungan Amerika Serikat, upaya menyingkirkan “pemilik tanah asli” tak pernah berhenti.
Bagi elite Israel, “bencana demografis” Palestina menuntut solusi permanen—dan salah satu keputusan besar yang lahir dari kekhawatiran itu adalah penarikan sepihak dari Jalur Gaza pada 2005.
Ariel Sharon, arsitek penarikan tersebut, menilai bahwa meninggalkan Gaza bukan semata strategi militer, melainkan langkah untuk mengurangi beban demografi yang menakutkan.
Sebab sejak awal berdirinya Israel pada 1948, Gaza selalu menjadi “simpul demografis” yang mengganggu proyek Zionis.
Dokumen-dokumen dan kesaksian sejarah menunjukkan, berbagai agresi militer yang melanda Gaza hanyalah babak-babak dalam proyek besar “rekayasa demografi paksa”.
Upaya sistematis untuk mengubah peta penduduk Palestina dengan kekerasan.
Upaya-upaya itu memang mengambil bentuk berbeda dari masa ke masa. Ia dimulai dengan pengusiran massal saat Nakba 1948, berlanjut dengan percobaan-percobaan gagal memindahkan penduduk setelah perang 1967, hingga mencapai puncaknya dalam perang dahsyat sejak 2023.
Di balik retorika “keamanan nasional”, yang tengah dijalankan Israel di Gaza sebenarnya adalah fase baru dari proyek panjang pengosongan manusia—yang dijalankan secara sistematis melalui perang, blokade, dan tekanan ekonomi, dengan satu tujuan: mencabut rakyat Palestina dari tanahnya.
Dari Nakba hingga agresi 3 serangkai
Ketika negara Israel diumumkan pada Mei 1948, dimulailah salah satu pengusiran massal terbesar dalam sejarah modern.
Sekitar 750.000 warga Palestina terusir dari rumah-rumah mereka akibat tembakan, pembantaian, dan penghancuran desa-desa.
Sekitar 200.000 di antaranya melarikan diri ke Jalur Gaza—menggandakan jumlah penduduk wilayah kecil itu dalam waktu singkat.
Sebelum 1948, penduduk Gaza hanya sekitar 80.000 jiwa. Namun setelah Nakba, komposisi demografisnya berubah drastis.
Dalam hitungan bulan, Gaza menjadi tempat berlindung bagi ratusan ribu pengungsi dari kota dan desa yang dihancurkan pasukan Israel.
Menjelang akhir tahun itu, wilayah sempit ini menampung antara 200.000 hingga 250.000 pengungsi yang kemudian ditempatkan di delapan kamp yang didirikan oleh badan PBB, UNRWA.
Pada awal 1950-an, muncul rencana pertama untuk memindahkan para pengungsi Palestina dari Gaza ke Semenanjung Sinai, Mesir.
Antara tahun 1953 dan 1955, diluncurkan proyek yang mengalokasikan sekitar 50.000 feddan (sekitar 210 kilometer persegi) di barat laut Sinai, untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman bagi warga Palestina.
Pada 14 Oktober 1953, UNRWA menandatangani perjanjian dengan pemerintah Mesir: Kairo menyediakan lahan, sementara Mesir berjanji mengalirkan air Sungai Nil untuk mengairi wilayah itu.
Meski dikemas dengan label “kemanusiaan”, warga Palestina segera menyadari makna tersembunyi di balik proyek tersebut—upaya untuk menyingkirkan mereka jauh dari tanah air dan menggugurkan hak untuk kembali.
Rencana itu pun disambut gelombang protes keras di Gaza. Setelah serangan Israel ke wilayah itu pada 28 Februari 1955, ribuan warga turun ke jalan menolak proyek pemukiman di Sinai.
Kesadaran kolektif rakyat, disertai penolakan politik yang kuat, menggagalkan proyek tersebut.
Pemerintahan Mesir di bawah Presiden Gamal Abdel Nasser akhirnya membatalkannya. Padahal, bila proyek itu terlaksana, sekitar 60.000 warga Palestina akan direlokasi secara paksa.
Namun, upaya untuk “mengosongkan Gaza” tidak berhenti di situ. Pada musim gugur 1956, ketika dunia fokus pada krisis nasionalisasi Terusan Suez, Israel melancarkan serangan bersama Inggris dan Prancis ke Mesir.
Di tengah perang itu, pasukan Israel memasuki Jalur Gaza untuk pertama kalinya sejak 1948 dan mendudukinya penuh pada November 1956.
Selama beberapa bulan pendudukan—hingga Maret 1957—tentara Israel melakukan pembantaian di berbagai wilayah. Sekitar 1.200 warga terbunuh di Khan Yunis dan Rafah saja, menurut catatan sejarah dan kesaksian warga.
Bersamaan dengan kekerasan itu, ratusan keluarga Palestina diusir ke arah gurun Negev dan mendekati perbatasan Mesir, bagian dari rencana untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza.
Dokumen Israel menyebut Menteri Keuangan waktu itu, Levi Eshkol, mengalokasikan dana sekitar 500.000 dolar AS untuk mendukung operasi ini—bagian dari strategi sistematis untuk “mengakhiri keberadaan Palestina” di Gaza.
Namun, rencana tersebut kandas. Rakyat Palestina melawan, Mesir menolak, dan tekanan internasional meningkat.
Di bawah tekanan AS dan Uni Soviet di PBB, Israel akhirnya menarik diri dari Gaza pada Maret 1957.
Pendudukan berakhir, tetapi ingatan akan pembantaian dan pengusiran itu tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Gaza.
Perang 1967: “Kita akan menyangkal rencana ini jika terungkap”
Pasca-perang 1967, pemerintah Israel membahas berbagai skenario mengenai masa depan Jalur Gaza.
Salah satu yang paling menonjol adalah rencana strategis untuk “mengosongkan” wilayah itu dari penduduk Palestina melalui apa yang disebut “migrasi sukarela”—langkah awal menuju aneksasi.
Dokumen resmi menunjukkan, Perdana Menteri Levi Eshkol mengusulkan penciptaan krisis kemanusiaan di Gaza dengan menghancurkan sektor pertanian kecil yang ada, agar penduduknya terdorong pergi karena tekanan ekonomi dan kelaparan.
Menteri Pertahanan saat itu, Moshe Dayan, bahkan lebih terbuka: ia menginginkan jumlah penduduk Gaza dikurangi dari 450.000 menjadi hanya 100.000 jiwa—jumlah yang menurutnya masih bisa “ditoleransi” oleh Israel.
Menurut artikel dalam Majalah Studi Palestina tahun 2025, rencana itu dijalankan di tengah tekanan internasional yang menolak pengusiran massal.
Karena itu, Dayan menegaskan bahwa operasi tersebut harus dirahasiakan.
“Kita akan menyangkal keberadaan rencana ini jika terungkap atau jika dibentuk komisi penyelidikan,” katanya dalam salah satu rapat kabinet.
Pada 19 Februari 1968, dibentuklah unit rahasia di bawah pemerintah Israel untuk mengoordinasikan pelaksanaan rencana itu—memfasilitasi dan “mendorong” warga Gaza untuk meninggalkan tanah mereka.
Rencana itu termasuk membuka jalur bebas menuju Tepi Barat, agar para pengungsi dapat melanjutkan perjalanan keluar negeri melalui perantara biro perjalanan dan pemerintah asing.
Pemerintah Israel menyiapkan dana besar, memberikan insentif berupa uang tunai dan bantuan logistik bagi mereka yang bersedia meninggalkan Gaza.
Negara-negara yang disasar sebagai tujuan antara lain Yordania, negara-negara Teluk, dan beberapa negara Eropa.
Namun, meskipun dijalankan secara rahasia dan dengan dukungan penuh pemerintah, rencana itu gagal total.
Mayoritas warga Gaza menolak pergi. Dari target ratusan ribu orang, hanya sekitar 20.000 yang meninggalkan wilayah itu—angka yang jauh dari sasaran.
Kegagalan tersebut tidak menghentikan gagasan dasarnya. Israel mengubah taktik: menggunakan pekerjaan sebagai kedok pemindahan.
Moshe Dayan kemudian mengusulkan pemindahan warga Gaza ke kamp-kamp di daerah Jericho dengan alasan penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dimaksudkan untuk memindahkan mereka ke Yordania.
Pada pertengahan 1968, pemerintahan militer Israel mulai menjalankan operasi pemindahan sekitar 50.000 pengungsi dari kamp Jabalia di Gaza Utara menuju Yordania.
Namun pemerintah Yordania segera menyadari arah rencana ini dan bertindak cepat.
Amman memberlakukan aturan ketat: setiap warga Gaza yang hendak masuk harus membawa izin tertulis dari Wali Kota Gaza, Rashad al-Shawa. Kebijakan ini efektif menggagalkan proyek tersebut.
Selain itu, para wali kota di Tepi Barat juga menolak menerima pengungsi dari Gaza meskipun Israel menawarkan dana dan investasi bagi daerah mereka.
Upaya menciptakan “penampungan alternatif” bagi pengungsi Gaza pun gagal.
Meski demikian, Israel tetap melanjutkan ide “migrasi sukarela” dengan jalur baru. Pada Mei 1969, laporan mengungkap bahwa badan intelijen Mossad menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Paraguay untuk menerima sekitar 60.000 warga Gaza sebagai pekerja migran.
Berdasarkan kesepakatan itu, Israel menanggung biaya perjalanan, sementara Paraguay menerima 33 dolar untuk setiap migran dan memberi izin tinggal selama 4 tahun.
Setelah lima tahun, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Paraguay sesuai hukum negara tersebut.
Namun lagi-lagi, proyek itu gagal total. Hanya segelintir orang yang berangkat melalui program tersebut.
Kesadaran rakyat Palestina terhadap bahaya rencana semacam itu semakin tinggi, dan keteguhan mereka untuk bertahan di tanah sendiri—apa pun risikonya—kembali menggagalkan proyek “pengosongan Gaza”.
Perang Oktober 1973: Gaza sebagai pusat perlawanan
Pasca-perang Oktober 1973, Israel tidak hanya sibuk menimbang untung-rugi di medan perang.
Negara itu menatap lebih jauh: menyusun sebuah proyek yang lebih berbahaya, yakni merancang ulang peta demografis kaum Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Wilayah yang sejak 1967 menjadi titik panas perlawanan dan batu sandungan bagi rencana-rencana pengendalian jangka panjang.
Ide ini bukanlah hal baru. Pada 1970, Ariel Sharon—komandan wilayah selatan Angkatan Darat Israel—meluncurkan sebuah rencana keamanan yang matang, yang intinya mengurung kamp-kamp pengungsi Palestina, menjadikannya “pulau-pulau” tertutup yang mudah dibongkar dan dikendalikan.
Inti rencananya adalah mendeportasi hingga 38.000 warga Palestina dari Gaza, melalui pemecahan struktur kamp dan meruntuhkan kohesi sosialnya.
Saat pelaksanaan dimulai, bulldozer Israel menghancurkan ribuan rumah di jantung kamp-kamp.
Jalan-jalan militer lebar dibuka di antara permukiman untuk memudahkan masuknya tank dan mencegah pejuang Palestina memanfaatkan gang-gang sempit sebagai saksi kelahiran perlawanan.
Menjelang musim panas Juli 1972, konvoi pengusiran telah mencapai Al-Arish di Mesir; sekitar 5.000 orang dipindahkan.
Sementara perkiraan Institut Studi Palestina menyebutkan jumlah pengungsi yang dikirim ke Sinai mencapai sekitar 12.000 jiwa.
Walau bagi sebagian pihak langkah itu tampak semata-mata sebagai tindakan keamanan, sesungguhnya ia adalah perpanjangan dari kebijakan yang lebih luas — kebijakan yang lahir sejak apa yang disebut “Rencana Allon” setelah kekalahan 1967.
Rencana itu mengusulkan penciptaan “kanton-kanton” Palestina yang terpisah dan terkurung, sebagai tahap awal mengosongkan atau meredistribusi penduduk tanpa pengumuman resmi.
Targetnya bukan sekadar soal keamanan; ia bermuatan demografis dan strategis. Pembongkaran kamp berarti menguras populasi Gaza sebagian demi sebagian, merobek ikatan historis antara rakyat Palestina dan tanah mereka.
Seperti upaya-upaya sebelumnya, rencana ini pun tak mencapai semua tujuannya. Meski dihimpit kemiskinan, blokade, dan pembongkaran rumah, penduduk Gaza tetap membumi pada tanahnya.
Banyak yang kembali setelah Perjanjian Camp David 1978, sementara Mesir, baik secara resmi maupun di tingkat rakyat, menolak dengan tegas mencampurkan rakyat Palestina ke Sinai — karena paham akan bahaya politik bagi hak-hak pengungsi dan keamanan nasional Mesir.
Kecaman internasional pun menguat; tindakan semacam itu dianggap pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran Konvensi Jenewa yang mengharamkan pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki.
Perang 1982: “Migrasi sukarela” yang terpola
Setelah perang 1982 di Lebanon, di samping tujuan militer untuk mengendalikan Gaza, Israel mulai mengimplementasikan strategi perpindahan senyap.
Strategi ini mengandalkan tekanan ekonomi, sosial, dan keamanan yang terorganisir untuk mendorong warga Palestina meninggalkan tanahnya secara—katakanlah—“sukarela”, tanpa pengumuman resmi.
Kebijakan itu dimulai dengan memperketat pergerakan pekerja dan pedagang, mengurangi izin kerja ke dalam Israel, serta penutupan perbatasan yang berulang.
Langkah-langkah tersebut memperparah pengangguran dan kemiskinan, memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza.
Secara paralel, Israel memperkuat kehadiran pemukiman lewat pembangunan permukiman seperti Netsarim dan Gush Katif.
Hal itu dihubungkan dengan jaringan jalan yang mengasingkan warga Palestina dan mempersulit kehidupan di Gaza, sehingga struktur sosialnya tercekik dan tercipta realitas demografis baru.
Dari sisi keamanan, otoritas Israel melakukan pembongkaran rumah yang luas atas dalih “keamanan”, memaksa ribuan warga mengungsi secara internal—menambah tekanan demografis.
Meski tanpa pengumuman resmi soal pembuangan massal, kombinasi tindakan ini mendorong ribuan orang meninggalkan Gaza untuk mencari peluang hidup di luar.
Dalam konteks itu, Mordechai Ben-Porat, menteri pada pemerintahan Menachem Begin, mengungkapkan sebuah rencana ambisius: memindahkan sekitar seperempat juta pengungsi Palestina dari Tepi Barat dan Gaza ke “wilayah baru”.
Tujuannya—menurut para pengusul—adalah menghapus muatan politik kamp-kamp pengungsi dan memutus kaitannya dengan hak kembali.
Rencana ini mendapat sambutan di lingkaran Begin namun dibekukan saat meletusnya perang Lebanon.
Walau tak pernah dinyatakan sebagai kebijakan resmi pemindahan massal, dinamika di lapangan menunjukkan adanya pola sistematis.
Sebuah “rekayasa cekik” ekonomi dan demografis yang menurut para ahli hak asasi manusia melanggar hukum humaniter internasional.
Penarikan namun disertai blokade: Gaza yang tercekik
Meskipun Israel menarik permukimannya secara sepihak dari Gaza pada 2005, tindakan itu tidak mengakhiri upaya untuk menekan penduduk Palestina.
Alih-alih, pola perpindahan tetap berlanjut dalam bentuk blokade ekonomi yang mencekik dan serangan militer berkala—mengantar Gaza ke ambang kehancuran.
Sejak 2007, blokade ketat diberlakukan, mematikan sendi-sendi ekonomi Gaza dan menekan layanan kesehatan hingga titik kritis.
Angka pengangguran dan kemiskinan melonjak. Serangkaian serangan udara Israel pada 2008–2009, 2012, 2014, 2018, dan hingga 2021, memperbesar kehancuran fisik dan sosial.
Pola serangan berulang ini menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak semata-mata soal keamanan Israel, melainkan juga untuk menakut-nakuti dan mendorong warga pergi.
PBB memperingatkan pada 2012 bahwa Gaza berisiko menjadi “tidak dapat dihuni” pada 2020—perkiraan yang hari demi hari semakin nyata.
Proyek Giyora Ayland 2010: “Alternatif regional” yang menggugat kedaulatan
Pada 2010, Giyora Ayland, mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, mempublikasikan sebuah proposal strategis berjudul “Alternatif Regional untuk Ide Dua Negara bagi Dua Bangsa” melalui Pusat Studi Strategis Begin–Sadat.
Proposal ini termasuk salah satu gagasan paling radikal untuk merombak peta geografi dan demografi Palestina, terutama Gaza.
Inti gagasan Ayland adalah memindahkan penduduk Gaza ke utara Sinai dengan memperluas kawasan Gaza secara geografis melalui pencaplokan lahan seluas 720 km² dari wilayah Mesir.
Bentuknya berupa persegi panjang yang membentang sekitar 24 km ke arah timur dari Rafah menuju Al-Arish, dan 30 km ke selatan ke dalam Sinai.
Tujuannya: menciptakan ruang yang lebih luas untuk ekspansi demografis Gaza sebagai pengganti gagasan negara Palestina merdeka.
Sebagai imbalannya, Palestina diminta mengorbankan bagian setara dari wilayah Tepi Barat untuk kepentingan pemukiman Israel, sementara Mesir akan diberi kompensasi berupa wilayah di barat daya Negev.
Menurut Ayland, solusi regional ini akan mengatasi masalah kepadatan dan krisis ekonomi Gaza sekaligus membuka jalan penyelesaian konflik di luar jalur politik yang macet.
Namun, di balik bungkus “praktis” dan “teknis” itu, tampak klaim lama yang diperbarui: upaya membersihkan masalah Palestina melalui rekayasa geografis dan pengosongan Gaza secara bertahap dengan dalih pembangunan dan solusi operasional.
Gagasan ini mendapat sambutan hangat di kalangan kanan Israel, namun ditentang keras oleh Mesir—secara resmi dan oleh opini publik—karena dianggap melanggar kedaulatan Mesir dan mengancam keamanan nasionalnya.
Selain itu, rencana itu dilihat sebagai upaya nyata untuk melemahkan hak kembali dan memlegitimasi pendudukan.
Walau tidak pernah diimplementasikan, gema gagasan semacam ini terlihat kembali dalam proposal-proposal berikutnya seperti “Kesepakatan Abad Ini” dan upaya-upaya memisahkan Gaza dari narasi nasional Palestina.
“Rencana renyelesaian” 2017: Singkirkan sepersepuluh penduduk Gaza
Tahun 2017 menyaksikan anggota Knesset—dan ketua partai Zionisme Agama—Bezalel Smotrich mempublikasikan apa yang disebutnya “rencana penyelesaian.”
Bukan sekadar kebijakan keamanan, ia merupakan gambaran terbuka tentang pemindahan massal yang disamarkan, menargetkan penduduk Gaza melalui konsep “migrasi sukarela”.
Smotrich menyerukan pemberian kompensasi finansial kepada warga Gaza yang bersedia meninggalkan wilayah itu.
Sebuah upaya untuk mengurangi populasi lebih dari dua juta menjadi antara 100.000 hingga 150.000 jiwa.
“Jika hanya 100.000 yang tertinggal di Gaza, diskusi pasca-perang akan berbeda total,” ujarnya.
Meski dipasarkan sebagai opsi damai, rencana ini sesungguhnya kelanjutan dari kebijakan tekanan hidup yang dirancang untuk memaksa pengosongan demografis.
Namun uniknya, rencana 2017 muncul dari lembaga legislatif sendiri—Knesset—sebagai dokumen publik yang secara terang menyatakan bahwa “masalah” adalah keberadaan warga Palestina itu sendiri, bukan tindakan mereka.
Pengamat menilai rencana ini sebagai wajah modern dari pembuangan sistematis terselubung—pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional.
Pemerintah Israel kala itu memilih untuk bungkam; keheningan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai toleransi atau penerimaan implisit.
“Kesepakatan abad ini” 2020: Pengusiran dalam balutan blokade
“Kesepakatan Abad Ini” yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2020 bukanlah sekadar peta jalan menuju perdamaian, melainkan rancangan halus untuk menghapuskan secara bertahap persoalan Palestina — terutama nasib Jalur Gaza.
Dalam dokumen itu, Gaza tidak lagi dilihat sebagai entitas politik, melainkan sebagai beban demografis yang harus dikurangi penduduknya.
Di balik janji investasi dan proyek-proyek pembangunan senilai miliaran dolar, terselip kenyataan bahwa sebagian besar proyek itu justru dirancang di luar Gaza — tepatnya di Sinai Utara, Mesir.
Rencana tersebut mencakup pembangunan kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan kompleks perumahan bersama bagi warga Palestina dan Mesir.
Semua itu tampak seperti upaya terselubung untuk mendorong warga Gaza meninggalkan tanah air mereka tanpa memberi perbaikan nyata atas kehidupan mereka di dalam wilayah yang terkepung.
Janji pencabutan blokade pun hanya muncul sebagai syarat: Gaza harus melucuti senjata perlawanan dan menerima ketentuan politik yang berat sebelah.
Sebagai gantinya, warga Palestina ditawari “pintu keluar ekonomi” yang dikemas dengan istilah pembangunan dan peluang investasi.
Namun, di balik itu tersembunyi ajakan halus menuju migrasi massal—pengusiran yang dibungkus dengan janji kemakmuran.
Yang lebih berbahaya, “Kesepakatan Abad Ini” secara terang-terangan memisahkan Gaza dari Tepi Barat secara politik.
Pemisahan ini mengindikasikan niat lama untuk memecah proyek nasional Palestina menjadi entitas-entitas kecil yang mudah dikendalikan dan diarahkan ke solusi regional seperti pemukiman ulang pengungsi di Sinai.
Dengan demikian, kesepakatan itu menyajikan bentuk baru dari pengusiran: bukan melalui perang terbuka, melainkan lewat tekanan ekonomi dan tipu daya pembangunan.
Apa yang gagal dicapai oleh bom dan tank, coba diwujudkan lewat uang dan blokade.
Perang Oktober 2023: Alasan baru untuk pengusiran
Gagasan mengusir penduduk Gaza ke Sinai dan negara-negara lain kembali mencuat segera setelah serangan 7 Oktober 2023.
Gagasan itu cepat mendapat tempat dalam wacana politik dan media di Israel — dibahas secara terbuka oleh para politisi dari partai koalisi maupun oposisi, serta tokoh opini publik, sebagai “solusi” bagi krisis kemanusiaan dan keamanan di Gaza.
Menurut sebuah dokumen resmi yang disusun di Kementerian Intelijen Israel pada hari-hari pertama perang, tujuan politik terkait penduduk sipil dianggap bagian tak terpisahkan dari tujuan militer.
Dokumen itu menyodorkan tiga skenario masa depan bagi warga Gaza:
- Tetap tinggal di tempat dengan kembalinya Otoritas Palestina;
- Tetap tinggal di bawah pemerintahan lokal baru dengan pengawasan Israel;
- Dihilangkan dari Gaza dan dipindahkan ke Sinai atau negara tetangga lain.
Dua skenario pertama ditolak. Dokumen tersebut menilai opsi pertama sebagai kekalahan strategis karena bisa mengakhiri perpecahan politik Palestina dan membuka jalan menuju negara merdeka.
Opsi kedua dianggap tidak memberi keuntungan strategis jangka panjang. Karena itu, dokumen mendorong pilihan ketiga — pemindahan penduduk — sebagai prioritas utama.
Sejalan dengan itu, Israel berupaya menggalang dukungan internasional bagi ide pengusiran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan meminta langsung kepada Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron — yang masing-masing berkunjung ke Israel — agar menekan Mesir menerima ratusan ribu warga Gaza di wilayah Sinai.
Dokumen itu juga merekomendasikan langkah-langkah lapangan untuk membuka jalur perpindahan ke selatan, menuju Rafah, dengan dalih operasi militer.
Kembalinya para jenderal
Pada September 2024, nama Giora Eiland — mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel — kembali mencuat lewat sebuah dokumen strategis yang disebut “Rencana Para Jenderal”.
Bersama sejumlah perwira senior, ia mempresentasikan peta jalan yang bukan sekadar kajian akademik, melainkan deklarasi niat.
Yaitu, “penyelesaian akhir” bagi keberadaan perlawanan di Gaza utara sekaligus langkah awal menuju pemukiman kembali wilayah itu oleh Israel.
Inti rencana tersebut sederhana sekaligus mengerikan: pengusiran paksa warga Gaza ke selatan, disertai pengepungan total dan kebijakan kelaparan sistematis di utara. Setiap orang yang tetap tinggal akan dianggap sebagai target militer.
Dengan kata lain, strategi ini memecah Gaza menjadi dua wilayah — memaksa warga memilih antara pengungsian internal atau kematian.
Rencana ini dijalankan dengan dua instrumen utama. Pertama, blokade dan kelaparan digunakan sebagai alat perubahan demografi — bukan lewat senjata, tetapi dengan mematikan syarat-syarat hidup.
Kedua, pemberian status militer pada kawasan sipil, yang memberi dalih hukum bagi penghancuran massal dan pengungsian besar-besaran.
Yang membuat rencana ini menakutkan bukan hanya isinya, tetapi juga waktu kemunculannya: di tengah perang yang sedang berlangsung, di saat dunia bungkam dan kawasan tak berdaya.
Kondisi itu membuat pelaksanaannya tampak realistis, sebab alat-alat yang dibutuhkan — penutupan perbatasan, blokade penuh, dan serangan terarah — sudah dijalankan oleh Israel selama perang pemusnahan di Gaza.
Secara politik, “Rencana Para Jenderal” mencerminkan pola lama dalam strategi Israel: mengubah realitas demografis sebagai jalan keluar dari “masalah Gaza”.
Bedanya, kali ini gagasan itu tidak lagi berhenti di ruang rapat, tetapi di tangan pihak-pihak yang punya kekuatan untuk melaksanakannya.
Karena itu, ia bukan sekadar dokumen pemikiran, melainkan proyek nyata dengan tanda tangan para jenderal — deklarasi terbuka untuk mencabut Gaza utara dari peta penduduknya dan menjadikannya wilayah tanpa orang Palestina.
Rencana ini, dengan demikian, bukan sekadar perang terhadap perlawanan, melainkan terhadap geografi, demografi, dan hak untuk tetap hidup.
Jika berhasil dilaksanakan, dunia akan menyaksikan bentuk baru dari pengusiran massal: bukan melalui bom semata, melainkan lewat kelaparan yang disusun rapi, kehancuran yang sistematis, dan kehidupan yang sengaja dibuat tak layak.
Sebuah bentuk “pengusiran diam-diam” yang meniadakan hak bertahan hidup — tanpa perlu mengumumkan perang secara resmi.
Visi Amerika Serikat: Pengusiran dalam wajah baru
Di tengah salah satu bab paling berdarah dalam sejarah Gaza, perbedaan sikap di dalam Gedung Putih terhadap isu pengusiran paksa mulai tampak jelas.
Meski secara publik Amerika Serikat menolak pengusiran, kebijakan nyata di lapangan menunjukkan paradoks antara kata dan tindakan — menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Washington terhadap hukum humaniter internasional.
Sejak awal perang, Presiden Joe Biden menegaskan berkali-kali bahwa Amerika menolak “pengusiran paksa dari Gaza”, menyebutnya sebagai “garis merah”.
Sikap ini juga disampaikan Departemen Luar Negeri, meski di saat yang sama lembaga itu mengaku khawatir Israel mungkin melampaui batas tersebut.
Di Kongres, lebih dari 60 anggota legislatif menyerukan agar pemerintahan Biden mengambil posisi tegas menentang setiap upaya perubahan demografis di Gaza, memperingatkan bahwa diamnya AS bisa dibaca sebagai “lampu hijau” terselubung bagi Israel.
Namun, retorika Biden tidak bebas dari kontradiksi. Dalam sebuah acara di Gedung Putih memperingati hari raya Yahudi Hanukkah, di hadapan tokoh-tokoh politik dan keagamaan Yahudi, Biden menyerukan agar “perbatasan dibuka bagi warga Gaza”.
Ia juga menyebut bahwa ia telah meminta langsung Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk menjamin hal itu.
Pernyataan tersebut dipandang sejumlah pengamat sebagai isyarat samar bahwa Washington bisa menerima eksodus warga Gaza — bertentangan dengan pernyataannya sendiri yang menolak pengusiran.
Indikasi lain muncul dalam proposal anggaran darurat yang diajukan Biden ke Kongres. Dari total miliaran dolar bantuan, sekitar 3,495 miliar dolar dialokasikan di bawah pos “bantuan migrasi dan pengungsi”.
Hal itu untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga terdampak konflik, termasuk warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Dana itu juga ditujukan untuk membantu negara-negara tetangga yang mungkin akan menampung pengungsi Gaza.
Sebuah langkah yang tampak seperti persiapan diam-diam untuk menghadapi skenario eksodus besar, meski tidak dinyatakan secara terbuka.
Secara keseluruhan, kebijakan Biden digambarkan para pengamat sebagai bentuk “diplomasi lunak” — tanpa tekanan nyata untuk menghentikan blokade atau menahan agresi militer Israel yang justru memperparah gelombang pengungsian.
Dalam pandangan para ahli hukum kemanusiaan, posisi AS lebih mirip “penyangkalan halus” ketimbang penolakan tegas.
Berbeda dengan Biden, Donald Trump pada masa kepemimpinannya justru lebih terbuka mendukung gagasan pemindahan warga Palestina.
Dalam versi awal “Kesepakatan Abad Ini” pada 2020, terselip gagasan pembangunan wilayah di Sinai yang bisa dijadikan “perpanjangan demografis” bagi rakyat Palestina.
Bahkan pada 2025, Trump menyatakan secara terbuka bahwa AS mungkin “akan mengelola Gaza” dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah”, sambil mengusulkan pemindahan sebagian penduduk ke negara-negara sekitar.
Di atas kertas, inisiatif Trump terbaru mengenai Gaza tampak menolak pengusiran paksa. Dokumennya bahkan menyebut secara eksplisit:
“Tidak seorang pun akan dipaksa keluar dari Gaza.”
Namun, realitas tak selalu ditulis dengan tinta. Dengan segala isyarat samar dan celah dalam pelaksanaan, janji itu kini menjadi ujian moral: apakah rencana tersebut sungguh ditujukan untuk membangun Gaza, atau sekadar menyusun bab baru dari kisah panjang pengusiran yang dibungkus dengan nama “perdamaian”.