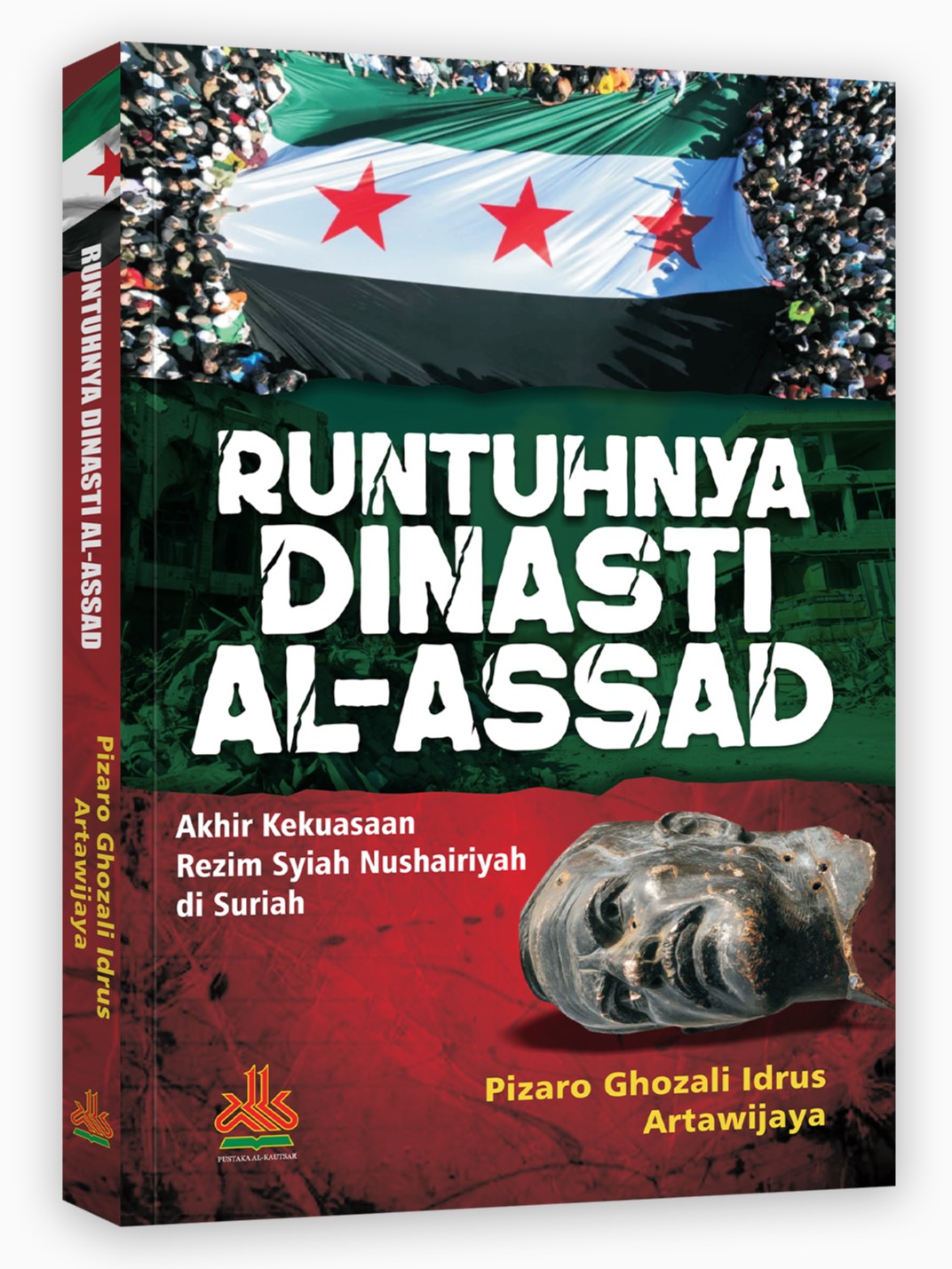Menjelang tengah malam, Ahad (10/8/2025), lima jurnalis Al Jazeera di Gaza berpulang dalam satu serangan udara Israel yang menghantam mereka ketika sedang bertugas.
Ledakan itu menghentikan detak jantung mereka, memadamkan kamera dan mikrofon, tetapi tak mampu menghapus jejak perjuangan dan suara mereka dari ingatan warga Gaza.
Anas Al-Sharif, Muhammad Qurayqa, Ibrahim Zahir, Mu’min Aliwah, dan Muhammad Nufal, 5 wajah yang selama ini menjadi jembatan berita dari Gaza ke dunia, menyingkap tirai kebisuan yang hendak dipaksakan oleh pendudukan.
Kini nama mereka menjadi simbol kehilangan, kesedihan, sekaligus teladan pengorbanan demi kata-kata yang merdeka.
Mereka disatukan bukan hanya oleh logo Al Jazeera, tetapi oleh keyakinan mendalam: di Gaza, jurnalisme bukan sekadar profesi.
Ia adalah amanah kemanusiaan dan nasional, sebuah misi perjuangan yang kerap dibayar dengan darah.
Anas Al-Sharif, suara dari utara
Ketika mesin perang Israel menutup rapat pintu-pintu masuk ke Gaza Utara bagi sebagian besar media, nama Anas Al-Sharif justru makin berkilau.
Ia menembus tembok sensor dan pembungkaman, melaporkan tanpa henti dari lapangan, tak gentar meski diancam langsung oleh militer Israel.
Lahir di Kamp Pengungsi Jabalia pada Desember 1996, Anas adalah suami dan ayah dua anak.
Lulusan Sarjana Broadcasting dari Universitas Al-Aqsa, ia memulai karier jurnalistiknya pada 2014 sebagai kontributor lepas, meliput dari titik-titik terpanas di Gaza Utara.
Namanya mencuat pada liputan “Aksi Kepulangan” 2018, dan kian dikenal dunia pada perang “Pedang Yerusalem” Mei 2021.
Dalam agresi yang dimulai Oktober 2023, ia dipercaya menjadi koresponden Al Jazeera untuk Gaza Utara—tugas yang diemban di tengah risiko mematikan.
Desember 2023, serangan udara menghancurkan rumahnya di Jabalia dan menewaskan ayahnya.
Keesokan harinya, ia kembali ke medan liputan, seakan kehilangan justru menambah nyalanya.
Dalam wasiatnya yang ditemukan keluarga setelah ia gugur.
“Jika kalian membaca ini, berarti Israel berhasil membunuhku dan membungkam suaraku. Tapi aku telah berjuang sekuat tenaga menjadi penopang dan suara bagi rakyatku,” tulisnya.
Muhammad Qurayqa, luka pribadi, tugas abadi
Muhammad Qurayqa lahir di kawasan Shujaiya, Gaza Timur, tahun 1992. Yatim sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya, Na’mah, yang mengabdikan hidup untuk membesarkannya.
Penyuka buku dan diskusi ini menempuh studi Jurnalistik di Universitas Islam Gaza, lulus 2014.
Ia sempat bekerja di sejumlah media lokal seperti TV Al-Aqsa dan Radio Al-Ra’i, lalu menjadi kontributor untuk kantor berita internasional.
Agustus 2024, ia bergabung dengan Al Jazeera sebagai koresponden di Kota Gaza.
Hidupnya di masa perang adalah rangkaian kehilangan. Rumahnya dihancurkan. Bersama sang ibu yang renta, ia mengungsi dari satu tempat ke tempat lain.
Maret 2024, pasukan Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Shifa, memisahkan Muhammad dari ibunya.
Ia ditangkap, sementara ibunya diperintahkan berjalan kaki sekitar 8 kilometer menuju selatan.
Beberapa hari kemudian, ia dibebaskan. Ia mencari ibunya, hanya untuk menemukannya terbujur tak bernyawa dua pekan kemudian, ditembak sniper Israel di kepala.
Luka itu menetap di hatinya hingga akhir hayat. Namun, Muhammad tetap di kotanya, meliput di tengah puing, memadukan duka pribadi dengan amanah profesi.
Mu’min Aliwah, sang insinyur pecinta lensa
Mu’min Aliwah lahir di Shujaiya pada 2002. Dikenal cerdas, ia diterima di Fakultas Teknik Universitas Islam Gaza, jurusan Teknik Komputer. Sebelum perang merenggut nyawanya, ia nyaris menyelesaikan studi.
Mu’min juga dikenal sebagai pemain sepak bola berbakat, pernah membela Gaza SC dan klub “Khadamat Shujaiya”. Ia piawai dalam pemrograman dan perbaikan perangkat elektronik.
Empat bulan sebelum gugur, ia bergabung dengan Al Jazeera sebagai juru kamera dan editor. Karya-karyanya, yang merekam keseharian Gaza di bawah kepungan bom, menjadi kesaksian visual yang menggugah.
Rumahnya di Shujaiya dihancurkan, namun kamera tak pernah lepas dari genggamannya hingga detik terakhir.
Ibrahim Zahir, di antara liputan dan evakuasi
Berakar dari Kamp Jabalia, Ibrahim memulai karier sebagai desainer grafis sebelum terjun ke dunia fotojurnalistik pada 2018, meliput Aksi Kepulangan untuk media lokal seperti “Al-Shamal Online”.
Dalam perang kali ini, ia adalah bagian penting dari tim Al Jazeera di Gaza Utara, kerap bertugas bersama Anas Al-Sharif.
Di luar tugas jurnalistik, ia juga menjadi relawan evakuasi medis, memadukan aksi kemanusiaan di medan perang dengan dokumentasi visual.
Ibrahim kehilangan sekitar 170 anggota keluarga dalam serangan Israel, seluruh rumah keluarganya hancur. Ia dikenal santun dan pekerja keras.
Di ponselnya, foto Anas Al-Sharif menjadi wallpaper—simbol persahabatan yang berakhir di garis yang sama.
Muhammad Nufal, dari setir ke garis depan
Muhammad Nufal berasal dari Jabalia. Awalnya ia bekerja sebagai sopir tim Al Jazeera, kemudian menjadi asisten kamera, memastikan peralatan aman dan tim tiba di lokasi liputan meski dihantam blokade dan bom.
Awal perang, rumahnya hancur oleh serangan udara. Ia selamat dari reruntuhan dengan patah tulang panggul.
Ia kehilangan banyak anggota keluarga, termasuk ibunya yang tewas dua bulan lalu dan kakaknya yang gugur saat pengepungan Jabalia.
Meski luka belum pulih sepenuhnya, ia kembali bekerja. Menyertai tim di lapangan, menghadapi risiko yang sama, hingga maut menyergap mereka bersama-sama.