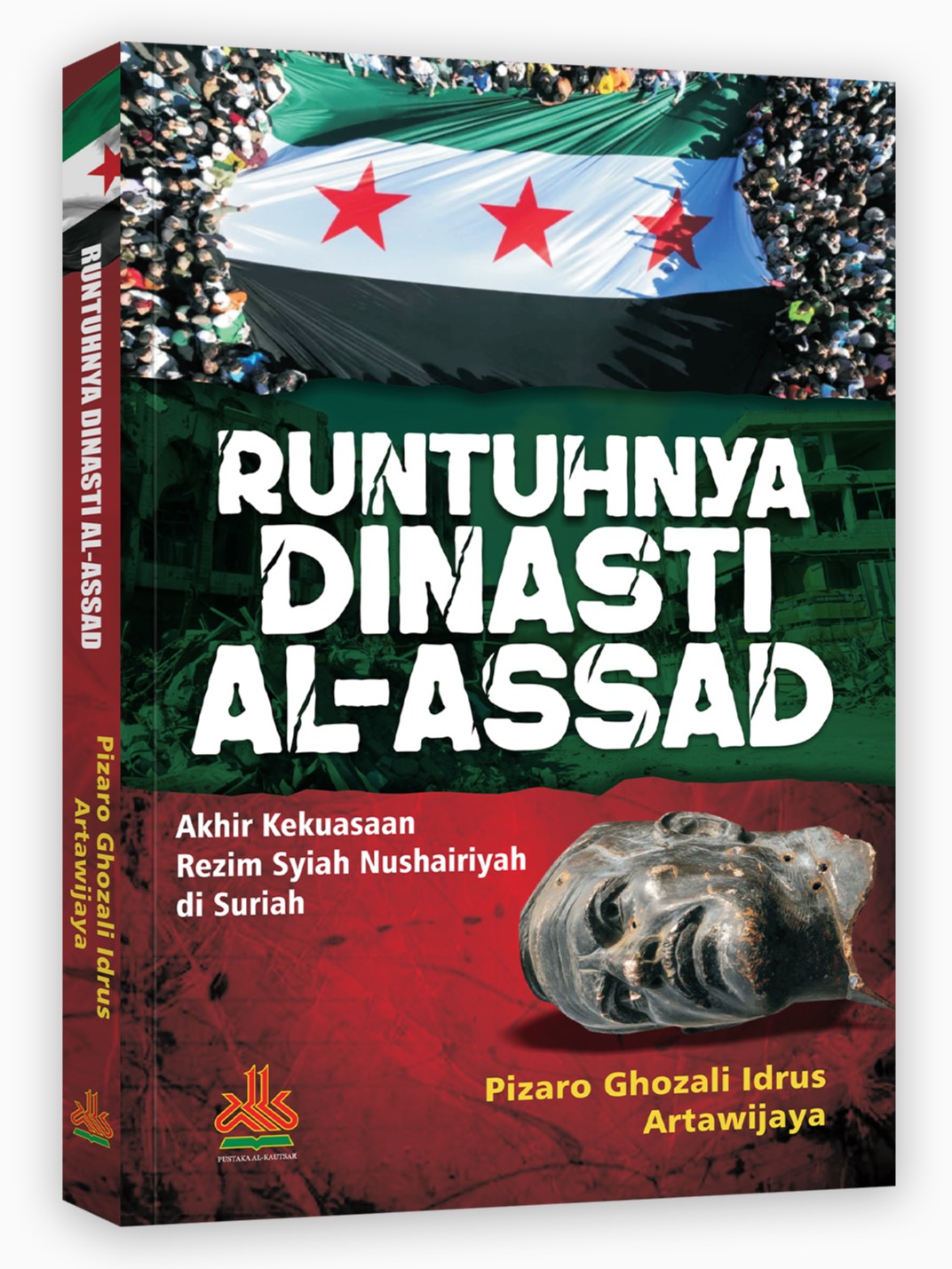Ketegangan antara Mesir dan Hamas mencapai titik puncak setelah Kairo mendukung seruan pelucutan senjata terhadap kelompok perlawanan Palestina itu.
Langkah ini, menurut sumber Mesir dan Palestina kepada Middle East Eye, telah memicu kebuntuan dalam perundingan gencatan senjata.
Perselisihan memuncak sejak akhir April lalu, ketika pemerintah Mesir menyampaikan pesan kepada pimpinan Hamas di Doha agar kelompok itu menyerahkan seluruh persenjataannya dan menarik pasukan dari Jalur Gaza. Tuntutan ini langsung ditolak oleh Hamas.
Dorongan pelucutan senjata mencerminkan tekanan yang kian besar dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab kunci.
Pada 29 Juli, Mesir bergabung dengan Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Liga Arab mendukung New York Declaration tentang solusi dua negara.
Di dalamnya menyerukan agar Hamas melepaskan kendali atas Gaza dan menyerahkan persenjataan kepada Otoritas Palestina.
Menurut sumber di Mesir, Kairo awalnya menolak mengaitkan isu pelucutan senjata dengan perundingan gencatan senjata.
Namun, di bawah tekanan berkelanjutan dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Mesir mengubah sikap dan menyesuaikan diri dengan upaya regional yang digambarkan sebagai “proses penyerahan diri”.
Sikap baru ini sejalan dengan prasyarat Israel — yang didukung Washington — untuk mengakhiri perang di Gaza.
Sebelumnya, Mesir bersikeras bahwa pelucutan senjata harus menjadi bagian dari penyelesaian politik yang lebih luas dan terikat pada penghentian pendudukan Israel.
Kairo menolak usulan yang mengharuskan Hamas melucuti senjata sebelum terbentuknya negara Palestina.
Sikap lama ini bahkan ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty saat kunjungan ke Washington pada Maret lalu.
Ia menilai tidak realistis meminta mediator mencapai secara politik apa yang gagal dicapai Israel melalui berbulan-bulan operasi militer.
Dua sumber diplomatik di Kairo menyebut perubahan kebijakan ini juga dipicu memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan macetnya jalur diplomasi.
Mesir sangat khawatir terhadap upaya Israel memaksa perpindahan penduduk Gaza ke Sinai utara.
Laporan pembangunan kamp tenda berskala besar di wilayah Rafah, dekat perbatasan Mesir, untuk menampung lebih dari 500.000 pengungsi memicu kecaman.
Banyak yang menyebutnya sebagai kamp konsentrasi. Situasi ini, ditambah kemarahan publik di Mesir atas tuduhan keterlibatan pemerintah dan respon yang dinilai lemah terhadap krisis, makin memperuncing ketegangan.
Kredibilitas Mesir dipertanyakan
Moataz Ahmadein Khalil, mantan duta besar Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menilai perubahan sikap Kairo mencerminkan pandangan Washington bahwa peran Mesir terutama sebagai alat untuk menekan Hamas agar menerima tuntutan Amerika dan Israel.
Menurut Khalil, persepsi ini lahir dari krisis ekonomi akut yang dialami Mesir serta ketergantungannya pada dukungan politik Amerika Serikat (AS) untuk memperoleh bantuan dari donor internasional dan regional, termasuk bantuan langsung dari Washington.
“Penyesuaian Mesir dengan agenda Amerika merugikan baik Mesir maupun Hamas. Mengikuti tuntutan Washington hanya akan mendorong mereka meminta lebih banyak lagi, dan pada akhirnya meruntuhkan kredibilitas Mesir sebagai mediator,” ujar Khalil.
Ia menambahkan, pendekatan ini gagal memanfaatkan posisi Mesir sebagai penengah untuk mengamankan kepentingan nasionalnya sendiri, terlepas dari tujuan Amerika atau Israel.
Rakyat Palestina merasa dikecewakan
Ketegangan antara Mesir dan Hamas mencapai puncaknya pada akhir Juli lalu, setelah pidato televisi Khalil al-Hayya, salah satu pimpinan senior Hamas yang berbasis di Doha.
Dalam pidatonya, Hayya menyampaikan seruan langsung kepada rakyat Mesir, termasuk para pemimpin agama, militer, komunitas, dan kalangan intelektual, untuk membantu memecah blokade Gaza.
“Rakyat Palestina merasa dikecewakan. Apakah saudara-saudara kalian di Gaza akan dibiarkan mati kelaparan, padahal mereka hanya berada di seberang perbatasan dan dalam jangkauan kalian?” ujarnya.
Hayya mengkritik pengiriman bantuan melalui udara yang ia sebut sebagai “sandiwara tragis” dan mengecam penutupan perbatasan Rafah antara Mesir dan Palestina.
“Kami memandang Mesir sebagai negara besar yang harus menyatakan dengan tegas bahwa Gaza tidak akan mati kelaparan, dan tidak akan membiarkan musuh terus menutup perbatasan Rafah terhadap kebutuhan Gaza,” katanya.
Seorang sumber keamanan Mesir mengatakan, pidato Hayya itu memicu kemarahan mendalam di Kairo.
Pemerintah menilainya sebagai hasutan terhadap negara dan upaya memojokkan Mesir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelaparan di Gaza.
Otoritas khawatir pernyataan tersebut dapat memicu gejolak publik dan mengancam stabilitas nasional.
Seruan untuk membuka paksa perbatasan Rafah juga dianggap sebagai ajakan berbahaya yang berpotensi menyeret Mesir ke dalam perang melawan Israel, sekaligus ancaman bagi keamanan nasional.
Sebagai respons, pemerintah Mesir melancarkan kampanye media keras terhadap Hamas. Sejumlah jurnalis dan platform daring pro-pemerintah mengkritik tajam kelompok itu.
Kepala State Information Service Mesir, Diaa Rashwan, menyebut pernyataan Hayya “sangat berbahaya”.
Sementara anggota parlemen Mostafa Bakry, yang dikenal dekat dengan dinas intelijen, mendesak pimpinan Hamas mengeluarkan pernyataan yang membebaskan Mesir dari tuduhan blokade dan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.
Seorang sumber di internal Hamas mengatakan kepada Middle East Eye bahwa seruan Hayya disampaikan dalam semangat niat baik, persaudaraan, dan harapan mendalam rakyat Gaza kepada Mesir, bukan sebagai hasutan.
Menurut sumber itu, di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza dan kebuntuan total dalam negosiasi politik.
“Satu-satunya pintu yang tersisa untuk diketuk adalah pintu saudara-saudara kami di Mesir,” terangnya.
Kementerian Luar Negeri Mesir tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar hingga berita ini dipublikasikan.