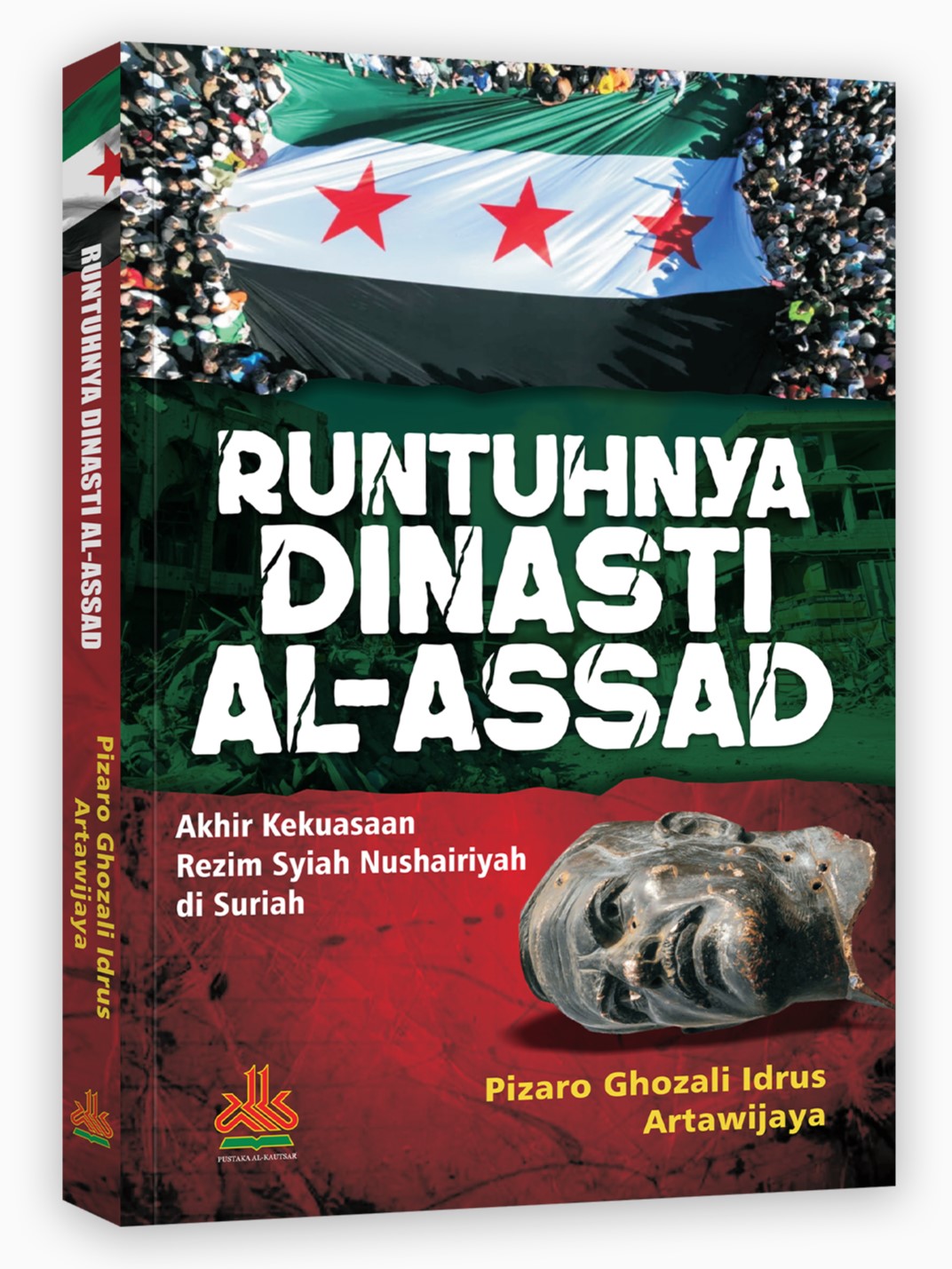Oleh: Dr. Ammar Ali Hassan
Militer Israel kembali memperlihatkan kebrutalannya terhadap dunia pers. Kali ini, sasarannya adalah dua jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh.
Keduanya dibunuh secara sengaja, sebagaimana diakui sendiri oleh militer Israel dalam pernyataan resminya.
Seolah-olah, mereka tak lagi peduli mempertahankan citra semu yang selama bertahun-tahun mereka jual kepada dunia: klaim sebagai “tentara paling bermoral di dunia”.
Padahal, sejarah panjangnya menunjukkan praktik “senjata pembunuhan” yang diarahkan terhadap politisi, jurnalis, dan warga sipil tak bersenjata—bahkan di luar masa perang.
Tidak mengherankan jika Al-Sharif dan Qreiqeh menjadi target. Selama berbulan-bulan terakhir, keduanya menjadi “mata dan telinga” dunia atas krisis kemanusiaan di Gaza—lapar, blokade, dan kebiadaban militer Israel.
Mereka bekerja dengan keberanian langka, hanya berfokus pada satu hal: membuka tabir kejahatan pendudukan dan mengirimkan suara warga Gaza yang terkepung.
Waswas itu telah mereka rasakan. Pesan terakhir Al-Sharif—yang bak wasiat—menunjukkan bahwa ia menyadari kematian akan datang, bahkan seolah menunggunya.
Ia dan Qreiqeh tahu betul bahwa liputan mereka adalah ancaman serius bagi Israel. Ancaman itu lahir dari profesionalisme dan keberanian mereka, di saat Israel melakukan segalanya untuk membungkam berita lapangan.
Ancaman itu nyata. Kedua jurnalis ini kerap menerima intimidasi langsung dari militer Israel, bahkan disebut media di Tel Aviv sebagai “mimbar hidup” yang terus-menerus mengekspos kebiadaban pasukan pendudukan.
Sejak dimulainya operasi “Thaufan Al-Aqsha”, Israel konsisten membungkam setiap suara yang menyingkap fakta genosida yang tengah berlangsung di Gaza.
Hampir 200 jurnalis Palestina telah dibunuh, lainnya ditangkap. Kantor media Arab ditutup, wartawan dilarang meliput, termasuk stasiun TV Al Mayadeen dan Al Jazeera. Kantor Al Jazeera di Ramallah pun disegel.
Pengetatan itu tak hanya menimpa media asing. Di dalam negeri, militer memberlakukan sensor ketat pada jurnalis dan komentator Israel yang mengkritisi pemerintah atau kebijakan perang.
Bahkan warga yang sekadar mengunggah rekaman kerusakan di dalam Israel pada bulan-bulan awal perang, atau saat Iran melancarkan serangan, ikut dibungkam.
Kini, kritik terhadap keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengorbankan sandera dan memaksakan invasi ke Gaza pun dibatasi.
Analisis awal atas pembunuhan Al-Sharif dan Qreiqeh mengarah pada satu Kesimpulan.
Yaitu, ini merupakan sinyal bahwa Israel tengah bersiap melakukan invasi penuh ke Kota Gaza, sebagaimana diputuskan kabinet Netanyahu beberapa hari lalu.
Kali ini, mereka akan mengerahkan kekerasan tanpa batas terhadap warga sipil—dengan risiko kejahatan yang lebih kejam dibanding sebelumnya.
Di Tel Aviv, suara-suara kritik mulai terdengar. Ada yang menyebut militer Israel mengalami “kegagalan total” di Gaza, bahkan menyamakan situasinya dengan kekalahan.
Sementara itu, faksi garis keras di pemerintahan terus mendorong agenda pengusiran massal warga Gaza secara permanen.
Selama perang kali ini, Israel melakukan pembungkaman media yang lebih ketat daripada perang-perang sebelumnya. Ada beberapa alasan:
- Menyembunyikan kerugian militer guna mengurangi tekanan dan kritik domestik, baik terhadap tentara maupun pemerintah.
- Melanjutkan propaganda “tentara bermoral”, mitos yang selama puluhan tahun dimanfaatkan untuk menutupi kejahatan terhadap warga sipil, di masa perang maupun damai.
- Menjaga citra “tentara yang tak terkalahkan” di mata para pendukung dan investor politik di Barat, yang memandang Israel sebagai “negara fungsi”—ujung tombak proyek geopolitik mereka di Timur Tengah.
- Memutus saluran komunikasi perlawanan Palestina agar aksi dan narasinya tak sampai ke dunia luar, terutama menjelang perang gerilya yang lebih sengit melawan pasukan invasi.
Israel kali ini berbeda. Dulu, mereka masih memberi sedikit ruang bagi media untuk melaporkan perang, demi tujuan propaganda dan perang psikologis. Kini, yang mereka inginkan hanyalah selubung gelap menutupi medan Gaza.
Faktor lain yang membuat Israel lebih represif adalah lamanya perang. Kebiasaan mereka adalah “perang kilat”—menang cepat, narasi tetap terkendali.
Kini, mereka terseret ke dalam perang gerilya yang melelahkan. Dalam kondisi ini, kerugian militer datang silih berganti, membuat tekanan publik di dalam negeri semakin berat.
Setiap kegagalan di medan tempur dibalas dengan kekerasan membabi buta terhadap warga sipil, jauh dari jangkauan lensa kamera dan mikrofon wartawan.
Pembunuhan Al-Sharif dan Qreiqeh adalah peringatan. Israel ingin mengintensifkan genosida dalam invasi darat yang akan datang.
Namun, itu juga menjadi bukti bahwa mereka tengah berjuang dalam perang yang jauh lebih sulit dari perkiraan awal.
Cepat atau lambat, tirai pembungkaman ini akan tersingkap. Saat itu, bukan hanya Netanyahu yang akan diadili oleh sejarah, tetapi seluruh proyek kolonial Israel akan menghadapi krisis legitimasi di mata para pendukungnya.
Al-Sharif dan Qreiqeh kini bergabung dengan para jurnalis yang gugur sebelumnya.
Namun, di Gaza, masih ada banyak yang siap mengangkat kembali “bendera kebenaran” untuk membongkar kejahatan pendudukan—meski itu berarti mempertaruhkan nyawa.
*Dr. Ammar Ali Hassan adalah seorang penulis dan peneliti sosiologi politik. Ia adalah seorang novelis dan pemikir Mesir yang lulus dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik, Universitas Kairo, pada tahun 1989. Ia meraih gelar doktor dalam Ilmu Politik pada tahun 2001. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Limādzā Aghtālat Isrāīl Anas al-Syarīf? Wa Mā ‘Alāqatuhu Bi iḥtilāl Kāmil Ghazati?”.