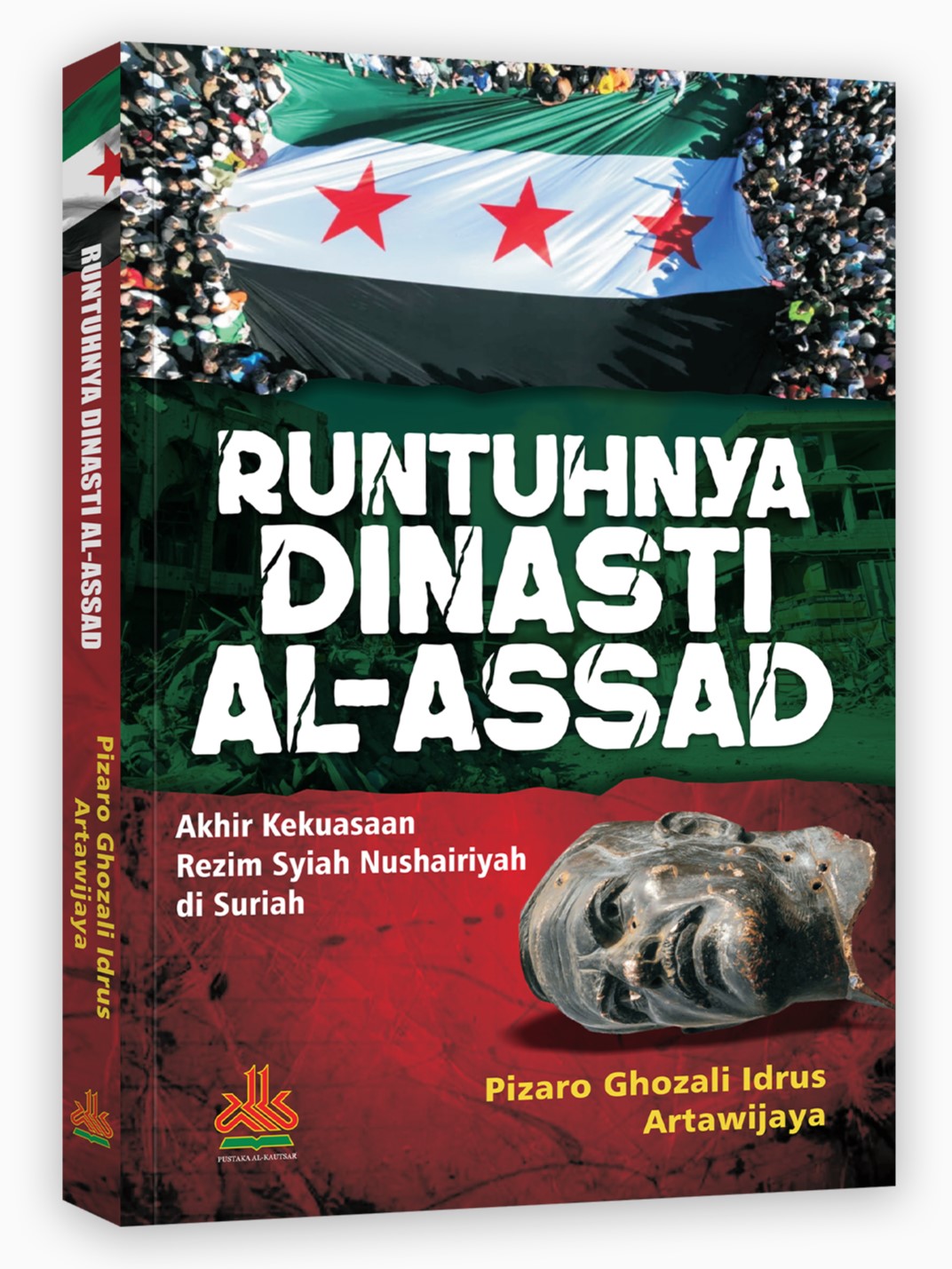Oleh: Kemal Öztürk
Di Turki, ada ungkapan lama yang berbunyi: “Semoga Tuhan tidak menguji siapa pun dengan kelaparan.”
Ungkapan ini lahir dari kesadaran akan betapa kejamnya kelaparan. Sebuah ujian yang mampu melucuti manusia dari nilai-nilai dan martabatnya, memaksanya kembali pada naluri paling purba: bertahan hidup dengan cara apa pun.
Kelaparan ditakuti bukan semata karena rasa lapar itu sendiri, melainkan karena ia menjadi batas akhir dari kemanusiaan. Ketika perut kosong, segala prinsip runtuh.
Ungkapan itu tiba-tiba terlintas di benak saya ketika tanpa sengaja mata saya menatap sebuah foto dari Gaza.
Foto seorang anak yang tinggal tulang dan kulit memeluk ibunya, yang tulangnya sendiri tampak menonjol di pipi.
“Semoga Tuhan tidak menguji siapa pun dengan kelaparan,” saya langsung berdo’a.
Namun pikiran saya tidak tertuju pada anak itu, bukan pula pada ibunya, dan bahkan bukan pada Israel—yang telah menjadikan kelaparan sebagai alat pembunuhan massal terhadap dua juta penduduk Gaza.
Saya teringat kalimat itu justru untuk dunia secara keseluruhan, umat manusia yang menyaksikan tubuh-tubuh kanak-kanak yang terkikis hingga tulang belulangnya terhitung satu per satu, dan tetap bungkam.
Dunia tengah diuji dengan kelaparan. Dan sejauh ini, ia gagal.
Makanan dan air—kebutuhan paling dasar manusia—diputus dari mereka yang terkepung. Mereka ditinggalkan mati perlahan dalam pengepungan yang dilakukan dengan penuh kesengajaan oleh Israel. Semua ini terjadi dalam diam yang memekakkan dari masyarakat global.
Bahkan, tak cukup bagi Israel untuk melarang makanan masuk ke Gaza. Ketika beberapa bantuan akhirnya berhasil menembus blokade, mereka yang mencoba membagikannya justru ditembaki.
Beberapa tewas sambil memeluk kantong tepung berlumuran darah. Dan dunia tetap saja diam.
Karena itu, jangan mudah tertipu oleh pernyataan diplomatis yang terdengar baik: “Bantuan harus segera dikirim ke Gaza.”
Selama perbatasan tetap tertutup, selama bantuan tidak bisa masuk dengan aman, selama gencatan senjata tidak terjadi, dan selama pembantaian terus berlangsung, maka semua kalimat itu hanya tinggal kata. Tak bermakna.
Orang-orang tewas karena kelaparan. Dan yang mencoba meraih sekarung tepung, tewas ditembak. Mereka yang tersisa mencoba memanggul kantong darah itu di atas bahu mereka.
Siapa pun yang melihat, bisa menghitung tulang belakang anak-anak Gaza. Bisa menghitung satu per satu tulang rusuk pria-pria dewasa yang kelaparan.
Dunia tengah menghadapi ujian kemanusiaan paling mendasar: ujian kelaparan. Tak satu pun lulus.
Dan kelak sejarah akan mencatat di bawah gambar-gambar kantong bantuan berlumur darah itu.
Di bawah tubuh-tubuh mungil yang tinggal kerangka, di bawah tatapan ibu yang memeluk anaknya dalam putus asa.
“Pada hari-hari itu, dunia diuji oleh kelaparan—dan semuanya gagal.”
Kalimat “Semoga Tuhan tidak menguji siapa pun dengan kelaparan” tak lagi tertuju bagi mereka yang kelaparan, melainkan untuk kita yang menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa.
Mungkin justru mereka yang mati kelaparan lebih beruntung dari kita, karena mereka tidak memiliki pilihan.
Anak-anak yang miskin, ibu-ibu yang tak berdaya, para ayah yang lelah, semua mereka terkepung, tak bersenjata, dan tak punya pelindung di hadapan salah satu mesin perang paling mematikan di dunia—dengan dukungan negara-negara adidaya.
Apa yang bisa mereka lakukan dengan tangan kosong? Karena itu, sejarah tidak akan menghakimi mereka. Anak cucu mereka tak akan menyesali mereka.
Tapi dunia—selain Gaza—memikul tanggung jawab moral. Negara-negara yang menutup pintu bantuan, yang tidak menjatuhkan sanksi, yang mengirim senjata, yang mendanai perang, yang memberikan dukungan politik, dan yang membutakan diri dari jeritan anak-anak kelaparan.
Semuanya akan tercatat dalam sejarah sebagai pelaku dan pendukung kejahatan.
Tak peduli agamanya—Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, atau tidak beragama.
Tak peduli rasnya, mazhabnya, atau latar belakang politiknya. Siapa pun yang gagal dalam ujian kelaparan ini, tak akan diampuni sejarah. Bahkan kuburannya kelak akan diadili oleh generasi mendatang.
Seperti halnya Hitler dan mereka yang mendukungnya terus dikenang sebagai simbol kekejaman.
Nama-nama seperti Netanyahu dan para pendukungnya akan menjadi catatan hitam sejarah manusia.
Foto anak-anak Palestina bertulang itu akan terus beredar. Dan setiap kali dunia melihatnya, akan dikatakan.
“Inilah Israel, negara paling kejam dalam sejarah kemanusiaan. Inilah Netanyahu, wajah paling tercela dari abad ini.”
Akan disebut satu per satu, para kepala negara yang memilih diam saat pembantaian terjadi.
“Inilah mereka yang tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan genosida ini.”
Dan dunia akan menyebut mereka dengan satu nama: komplotan kejahatan.
Dan kita juga—kita, warga biasa—akan memikul bagian dari rasa malu itu.
Begitulah wajah kegagalan dunia dalam ujian kelaparan. Percayalah, sejarah tidak akan melupakannya.
*Kemal Öztürk adalah seorang jurnalis Turki. Ia merupakan direktur berita, penulis, pembuat film dokumenter, dan Manajer Umum Anadolu Agency hingga 1 Desember 2014. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Al-Fāsyilūn Fī Imtiḥān al-Jū’i”.