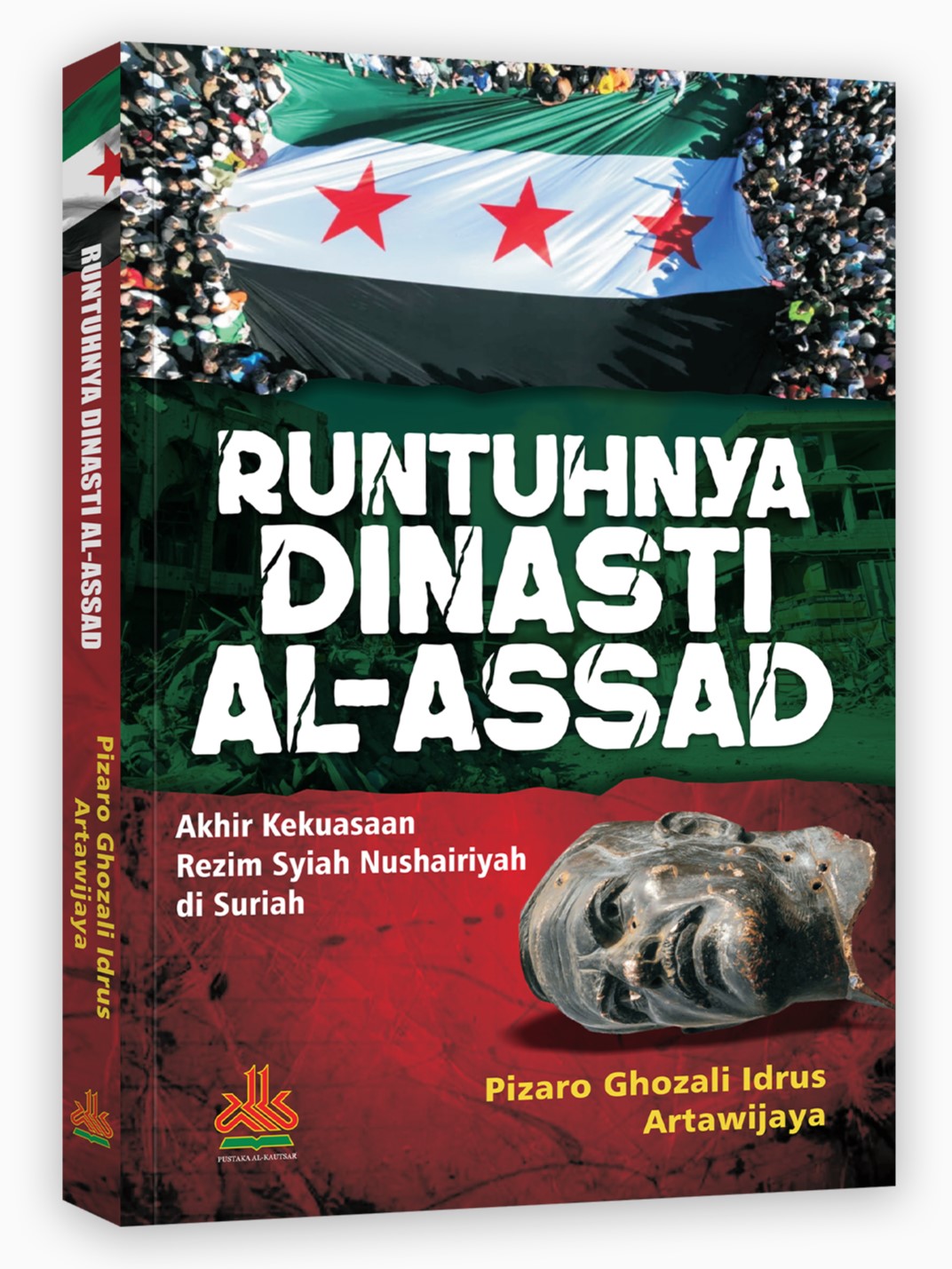Oleh: Dr. Saeed Al-Hajj*
Hampir 2 tahun sejak perang berkecamuk di Gaza dan kawasan sekitarnya, Israel telah menunjukkan superioritas militer dan keamanan yang tak terbantahkan, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).
Keunggulan ini membuatnya mampu menjatuhkan kerugian besar kepada semua lawannya. Namun, sampai hari ini, kemenangan mutlak yang bisa diumumkan secara resmi tak kunjung diraih.
Superioritas militer tak cukup
Sejak awal, Israel berupaya “menghapus” jejak Operasi Thaufan Al-Aqsha yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023, baik dari kesadaran publik maupun ingatan sejarah.
Serangan itu menjadi aib nasional yang mengguncang kepercayaan terhadap sistem keamanan dan militer Israel.
Untuk menutup luka itu, Israel melancarkan kampanye militer masif, dengan pendekatan baru. Bukan lagi menunggu ancaman datang, tetapi mencegah kemunculannya dengan kekuatan brutal dan penghancuran total.
Kebijakan ini melahirkan tindakan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Puluhan ribu warga sipil tewas, ratusan ribu lainnya terluka dan mengungsi, serta sebagian besar infrastruktur sipil dan institusi pemerintahan hancur.
Di sisi perlawanan, kerugian juga besar—baik dari segi logistik, sumber daya manusia, maupun struktur kepemimpinan.
Di luar medan tempur, Israel memperketat pengepungan dan blokade, memaksa kelaparan dan pengungsian massal, untuk mendorong negosiasi dengan posisi terkuat.
AS memberikan perlindungan diplomatik penuh, memungkinkan Israel bertahan dari tekanan internasional.
Selain Gaza, Israel juga memperluas serangan ke berbagai front. Di Lebanon, Israel melancarkan operasi militer besar terhadap Hizbullah.
Serangkaian pembunuhan terhadap tokoh penting, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah, dilakukan.
Ratusan serangan udara menargetkan gudang senjata dan rudal strategis milik Hizbullah.
Meski tercapai kesepakatan gencatan senjata, Israel tetap melanjutkan serangan sporadis, sembari mendorong opini publik Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut.
Di Suriah, Israel mengambil langkah sepihak dengan membatalkan perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974.
Wilayah baru diduduki, sumber air dikuasai, dan istana kepresidenan diserang. Bahkan, Israel secara terbuka mengancam akan membunuh Presiden Ahmad al-Sharaa dan mendukung minoritas di dalam negeri untuk mempercepat fragmentasi Suriah.
Sementara di Iran, dalam “Perang 12 Hari”, Israel mengoordinasikan serangan udara bersama AS terhadap infrastruktur militer dan nuklir Iran, termasuk sistem pertahanan udara dan fasilitas pengayaan uranium.
Yaman juga tak luput, dengan serangan berulang ke pelabuhan penting Hudaydah dan berbagai target strategis lainnya.
Namun, tak ada kemenangan yang jelas
Dengan agresi seluas ini, kesan yang muncul adalah bahwa Israel telah menundukkan semua musuh dan menata ulang peta kekuatan kawasan sesuai kehendaknya.
Namun, itu tidak lebih dari gambaran ilusi yang dibentuk oleh propaganda Israel untuk meraih keuntungan politik dalam negeri dan pengaruh global.
Gaza tetap menjadi titik balik paling menyakitkan bagi Israel. Meskipun dikepung total dan nyaris tanpa bantuan luar, kelompok perlawanan seperti Brigade Izzuddin al-Qassam masih bertahan.
Mereka tidak hanya mampu melancarkan serangan, tetapi juga berupaya kembali menangkap tentara Israel sebagai alat tawar dalam negosiasi.
Kartu sandera inilah yang menjadi kekuatan strategis utama mereka, bukti bahwa Israel belum benar-benar menang.
Di Lebanon, Hizbullah memang mengalami kerugian besar, terutama di wilayah selatan yang kini hampir bebas dari senjata.
Namun, kelompok itu belum menunjukkan tanda menyerah. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Na’im Qasim, bahkan menyatakan kelompoknya telah memulihkan kekuatan dan siap untuk konfrontasi baru jika diperlukan.
Iran pun perlahan bangkit dari pukulan awal. Laporan-laporan intelijen menunjukkan bahwa Teheran kini justru menggencarkan perang asimetris, termasuk serangan siber dan drone yang menyasar titik-titik lemah di dalam wilayah Israel.
Bahkan, setelah fasilitas nuklir diserang, kemampuan Iran dalam bidang ini belum lumpuh total.
Beberapa analisis memperkirakan program itu bisa dipulihkan lebih cepat jika ada keputusan politik.
Yaman, yang mungkin dianggap front terlemah, justru menunjukkan perlawanan paling konsisten.
Gerakan Ansarullah tetap aktif dengan retorika keras terhadap Israel, khususnya atas blokade Gaza.
Mereka bahkan berjanji untuk meningkatkan eskalasi jika perang kelaparan terus dilanjutkan.
Kesimpulan
Keunggulan militer dan intelijen Israel yang masif—hasil puluhan tahun pembangunan sistematis dengan dukungan langsung dari AS—memang memberinya kemampuan untuk melancarkan serangan besar-besaran.
Israel mampu menimbulkan kehancuran dahsyat, membunuh tokoh-tokoh penting musuhnya, melakukan infiltrasi mendalam, dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama di Gaza.
Namun, semua itu belum pernah sekalipun cukup untuk menciptakan kemenangan. Bahkan sekadar mengklaim kemenangan pun tak mampu dilakukan secara sah.
Israel berusaha membingkai kerugian besar yang ditimbulkannya sebagai hasil akhir dari perang.
Narasi ini kadang diamini sebagian pihak—baik karena minimnya informasi, tekanan akibat krisis kemanusiaan yang mencekik, maupun karena pertimbangan politik tertentu.
Tetapi kesimpulan seperti ini tidak akurat. Bukan karena meremehkan nilai nyawa manusia—baik mereka yang gugur, terluka, tertawan, maupun yang terusir dan kelaparan.
Juga bukan karena menafikan kekuatan militer Israel dan besarnya dukungan internasional yang mengiringinya.
Namun yang perlu dipahami, semua itu adalah bagian dari parameter evaluasi konflik, bukan hasil akhirnya.
Dalam banyak kasus sejarah, pihak yang menderita kerugian terbesar justru keluar sebagai pemenang.
Hal ini berlaku tidak hanya pada negara, tetapi lebih-lebih pada gerakan perlawanan dan pembebasan nasional melawan penjajahan.
Apalagi, kekejaman Israel terhadap warga sipil bukan hanya efek samping perang, tetapi dilakukan secara sengaja dan sistematis.
Karena itu, sangat penting untuk tidak terjebak dalam kerangka analisis yang dibentuk oleh kekerasan itu sendiri.
Lebih jauh lagi, perang yang sedang berlangsung saat ini belum mencapai titik akhirnya.
Bahkan jika pertempuran melambat atau jeda sementara terjadi, sifat konflik ini adalah jangka panjang, dengan potensi untuk kembali meletus setiap saat. Terutama bila menilik ambisi politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutunya yang terang-terangan menyasar perubahan peta kawasan.
Satu hal yang juga perlu dicatat: setiap kali pihak lawan menunjukkan itikad untuk berdamai atau menahan diri, justru Israel merespons dengan kekerasan yang lebih brutal. Hal ini terlihat di Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Iran.
Akhirnya, hasil dari Operasi 7 Oktober 2023 masih tetap terasa. Ia belum terhapus dan belum dilupakan. Peristiwa itu akan terus menjadi pijakan dalam perubahan dinamika politik dan militer ke depan.
Sementara dampak-dampak jangka panjangnya masih terus berkembang dan belum sepenuhnya terbaca.
Bisa jadi kita sedang berada di akhir dari satu babak, atau justru memasuki fase baru dari perang yang lebih panjang.
Karena itu, logika yang paling rasional saat ini bukanlah melemah dan menyerah pada tekanan, melainkan memperkuat posisi, menambah daya tahan, dan meningkatkan tekanan balik terhadap Israel.
Jika tidak, krisis kemanusiaan yang dipaksakan oleh Israel justru akan berubah menjadi “kemenangan strategis” baginya—dan itulah yang harus dicegah. Yang dibutuhkan kini adalah keteguhan, bukan kompromi.
*Dr. Saeed Al-Hajj merupakan penulis dan peneliti urusan Turki. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Limādzā Ta’jiz Isrāīl ‘An al-Intishār Ḥatā al-Ān?”.