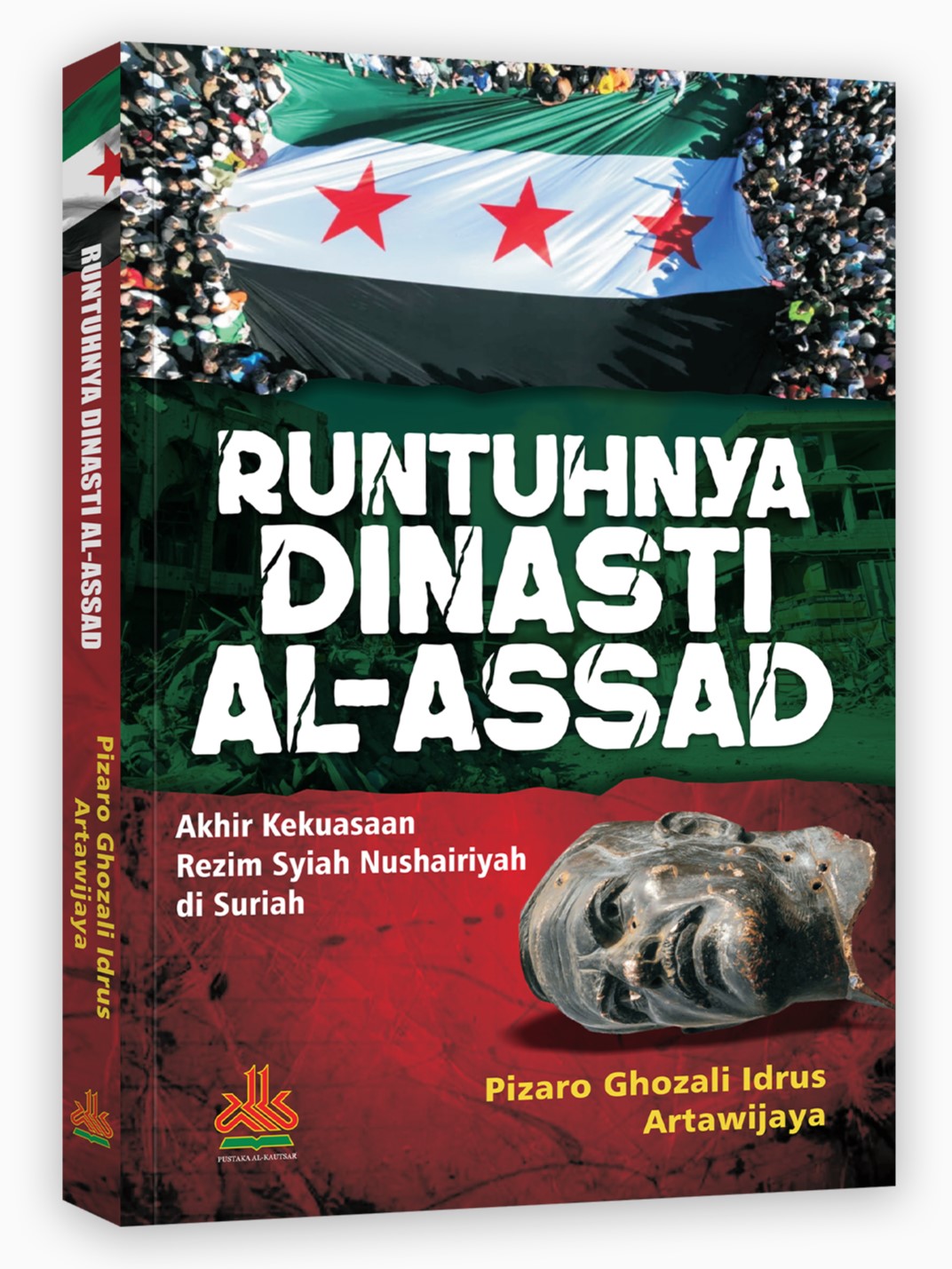Oleh: Ahmed Al-Hila*
Di tengah derasnya rumor negatif dan pernyataan tajam dari utusan Amerika Serikat (AS), Steven Witkoff, serta Presiden Donald Trump yang menuding Hamas tidak sungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan bahkan mengancam akan “melenyapkannya”, muncul klarifikasi penting dari dua negara mediator utama.
Pada 25 Juli lalu, pernyataan bersama dari Kementerian Luar Negeri Qatar dan Mesir menyatakan bahwa proses negosiasi justru mengalami kemajuan.
Mereka menegaskan bahwa berbagai kebocoran informasi di media tidak mencerminkan realitas perundingan yang sebenarnya.
Bahkan, disebutkan bahwa keluarnya delegasi dari meja perundingan lebih bersifat teknis untuk keperluan konsultasi internal dan dapat segera diikuti dengan kelanjutan dialog.
Informasi penting
Sinyal positif lainnya datang dari Bishara Bahbah, seorang pengusaha Amerika keturunan Palestina yang terlibat dalam mendekatkan posisi para pihak, bekerja sama dengan utusan AS Steven Witkoff.
Dalam wawancara publik pada hari yang sama, Bahbah mengungkapkan informasi penting yang ia peroleh langsung dari mediator Qatar dan Mesir.
Menurutnya, respons Hamas cukup positif dan menjadi dasar yang bisa dikembangkan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa Hamas tidak bersikap kaku, melainkan menunjukkan sikap siap untuk memberi dan menerima.
Lebih lanjut, Bahbah menjelaskan bahwa ketika pihak mediator menyerahkan tanggapan Hamas kepada Israel, pihak Israel mengisyaratkan bahwa mereka akan menanggapinya dengan hati-hati namun tetap terbuka.
Menariknya, menurut Bahbah, Hamas menyatakan bahwa isu pertukaran tawanan tidak menjadi penghalang utama dalam perundingan, sebab yang lebih krusial adalah peta wilayah.
Khususnya terkait penolakan terhadap kehadiran militer Israel di kawasan permukiman di Gaza.
Penuturan Bahbah secara tidak langsung membantah narasi dari sebagian sumber Israel yang menyebut bahwa pembekuan negosiasi disebabkan oleh tuntutan keras Hamas terkait tahanan.
Hamas sendiri dalam beberapa pernyataannya telah menegaskan bahwa isu tahanan tidak akan dibahas sebelum tercapainya kesepakatan kerangka dasar, yang mencakup penghentian perang, penarikan pasukan, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Konsistensi juga tampak dalam pernyataan resmi Hamas, yang menegaskan bahwa mediator, khususnya Qatar dan Mesir, menghargai posisi Hamas yang dinilai serius dan konstruktif.
Mereka menyebut telah mengupayakan pengurangan kedalaman zona penyangga Israel selama masa transisi 60 hari, dan menghindari daerah-daerah padat penduduk, agar sebanyak mungkin warga dapat kembali ke tempat tinggalnya.
Pernyataan-pernyataan ini—baik dari Bishara Bahbah maupun dari pihak Hamas—sejalan dengan isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar yang menegaskan bahwa proses negosiasi sejauh ini berjalan di jalur yang benar.
Dengan demikian, posisi Israel dan AS yang tiba-tiba berubah menjadi keras terlihat tidak berdasar secara objektif.
Patut pula dicatat bahwa dalam pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait penarikan delegasi Israel dari Doha, alasan yang disampaikan kala itu adalah untuk keperluan konsultasi internal.
Bahkan, pernyataan tersebut masih memuji peran positif Qatar dan Mesir, tanpa menampilkan nada negatif terhadap proses yang sedang berlangsung.
Alasam Israel balik arah
Perubahan sikap Israel dalam proses negosiasi gencatan senjata di Gaza bukanlah semata-mata reaksi spontan terhadap dinamika diplomatik.
Ia merupakan bagian dari pola yang lebih besar dan berulang: upaya menggagalkan kesepakatan yang tidak sejalan dengan agenda jangka panjang Israel dan pendukung utamanya, AS.
Dalam hal ini, sikap keras Washington—baik dari Presiden Trump maupun utusannya, Steven Witkoff—kembali memperlihatkan bahwa AS tidaklah bertindak sebagai mediator netral, tetapi sekutu penuh yang menyokong setiap langkah Tel Aviv, baik secara diplomatik maupun militer.
Kontras yang mencolok antara narasi Amerika-Israel yang bernada negatif dengan narasi Qatar, Mesir, dan Hamas yang lebih optimistis menunjukkan adanya dinamika yang lebih kompleks di balik layar.
Setidaknya, ada empat faktor utama yang menjelaskan mengapa Israel tiba-tiba menarik diri dari lingkungan negosiasi yang sebelumnya dinilai positif.
Pertama, Hamas berhasil memaksakan peta baru penempatan pasukan Israel selama masa transisi—yang menunjukkan adanya konsensus internal Palestina dan diterima oleh mediator Mesir dan Qatar.
Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan diplomasi Hamas, tetapi juga menandai penolakan tegas terhadap desain Israel yang ingin tetap bercokol di Gaza.
Kedua, peta-peta yang disodorkan Hamas secara eksplisit menolak pemutihan keberadaan militer Israel di wilayah permukiman warga sipil dan tidak memberi ruang bagi kelanjutan pengungsian massal ratusan ribu warga Palestina.
Hal ini memicu kegusaran Israel karena menggagalkan rencananya untuk membangun zona-zona penahanan luas yang mereka sebut sebagai “kota-kota kemanusiaan”. Istilah yang justru menutupi agenda pemindahan penduduk secara sistematis.
Ketiga, mundurnya Israel, yang dibalut dengan dalih teknis, bisa pula dibaca sebagai manuver negosiasi.
Dengan mengulur waktu dan mengintensifkan tekanan militer—mulai dari serangan udara hingga pengepungan total—Israel tampaknya berharap Hamas akhirnya menyerah dan menerima syarat-syarat yang diajukan Tel Aviv.
Pada intinya, mereka tetap ingin menguasai sebagian besar wilayah Gaza dan menjaga keberlangsungan pengungsian internal yang kini melibatkan sekitar 700 ribu warga.
Keempat, jika Hamas tetap bertahan dan Israel gagal memaksakan syaratnya, maka satu-satunya jalan keluar bagi Israel adalah menerima perjanjian yang sejalan dengan peta baru yang lebih menguntungkan warga Palestina.
Itu berarti pengakhiran agresi, penarikan pasukan secara menyeluruh, kembalinya pengungsi, serta masuknya bantuan kemanusiaan yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa—semua hal yang selama ini coba dihindari Israel.
Gagalnya skenario tekanan total inilah yang tampaknya mendorong Israel—dengan dukungan langsung AS—untuk membatalkan momentum positif yang telah dibangun selama negosiasi.
Sebuah pola yang sudah sering terjadi: ketika Israel merasa terpojok oleh kemajuan perundingan.
Mereka berbalik menyalahkan Hamas melalui kampanye media yang gencar, membanjiri ruang publik dengan informasi keliru yang dikutip dari “sumber terpercaya”, atau langsung dari pejabat tinggi yang tidak segan-segan menyebar disinformasi.
Kampanye ini bertujuan menggiring opini publik dunia untuk memaklumi stagnasi negosiasi dan membenarkan eskalasi militer lanjutan.
Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar, dan juga oleh Bishara Bahbah yang dekat dengan Witkoff, serta oleh Hamas sendiri, proses menuju kesepakatan sebenarnya sedang berada di jalur yang cukup menjanjikan.
Benang merah yang menghubungkan semua manuver Israel ini—baik yang bersifat militer maupun diplomatik—adalah satu: menciptakan kekalahan psikologis di kalangan rakyat Palestina, agar mereka akhirnya menerima skenario pengusiran dan kontrol wilayah dalam balutan perjanjian politik.
Dan selama tujuan ini belum tercapai, Israel tampaknya akan terus mencari cara untuk menggagalkan setiap proses damai yang tidak sejalan dengan agenda tersebut.
Israel dan kebuntuan strategisnya
Israel telah lama terbiasa duduk di meja perundingan bukan untuk bernegosiasi sejati, melainkan untuk memaksakan syarat dan visinya dengan kekuatan militer yang ditopang oleh dukungan AS yang nyaris tak tertandingi.
Namun, kali ini, situasinya berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern ini, Israel menghadapi lawan yang tetap bertahan meski terkepung dan dilanda bencana—yakni Hamas dan faksi-faksi perlawanan Palestina—yang menolak tunduk pada tekanan maupun menyerah kepada dominasi kekuatan.
Pertanyaannya: bagaimana mungkin sebuah gerakan perlawanan yang terisolasi secara geografis dan terbatas secara material mampu menahan tekanan negara yang paling bersenjata di kawasan itu, sementara rakyatnya tengah menghadapi genosida dan pembersihan etnis, dibunuh, dilaparkan, dan dipaksa mengungsi?
Inilah yang menjadi titik kebuntuan dan kegelisahan utama bagi Israel dan sekutunya di Washington.
Sebab semua jalan telah ditempuh—dari agresi brutal hingga blokade total, dari perang psikologis hingga pemerasan diplomatik—namun tujuan utamanya belum tercapai.
Pendekatan militer yang diluncurkan sejak dua tahun terakhir tak mampu mematahkan perlawanan rakyat Palestina, dan tak juga berhasil memulihkan “efek gentar” yang dulu melekat pada citra kekuatan militer Israel.
Bagi sebagian besar elite di Tel Aviv, ini bukan semata soal operasi militer, tetapi soal harga diri politik dan simbol kekuasaan.
Kekalahan simbolik yang mereka rasakan sejak serangan 7 Oktober 2023 dalam Operasi Thaufan Al-Aqsha terus membekas.
Serangan itu bukan hanya menembus sistem keamanan Israel, tetapi juga menjungkirbalikkan mitos keunggulan dan dominasi militernya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini berada dalam posisi yang rumit: tampak seolah berada di atas angin, namun sejatinya dikepung kegagalan.
Ia belum mampu menghancurkan Hamas, belum berhasil memulangkan para tawanan, dan gagal memadamkan semangat perlawanan warga Palestina.
Sementara itu, militer Israel semakin kelelahan, dan para jenderalnya mulai mengakui bahwa target politik tidak dapat diraih dengan kekuatan militer semata.
Yang lebih mengkhawatirkan bagi Netanyahu adalah dimensi politik domestik. Ia berharap keberlanjutan perang di Gaza bisa menjadi modal elektoral menjelang pemilu legislatif tahun depan, apalagi setelah mendapatkan dorongan popularitas dari konflik terbatas dengan Iran.
Namun jika jalur negosiasi gagal menghasilkan “kemenangan politik”, maka perang Gaza justru bisa menjadi beban besar yang menggerus dukungan publik, mengingat luka yang ditinggalkannya terus menganga dalam ingatan kolektif masyarakat Israel.
Dampak dari situasi ini pun melampaui ranah internal Israel. Secara internasional, citra negara yang dulu berhasil menjual dirinya sebagai “korban” kini telah runtuh.
Dunia semakin menyaksikan wajah asli Israel: negara pemukim bersenjata yang menyerang warga sipil dan melanggar hukum kemanusiaan.
Retorika “membela diri” tak lagi laku saat dunia menyaksikan kehancuran sistematis terhadap infrastruktur sipil, rumah sakit, dan anak-anak di Gaza.
Di sinilah letak awal dari krisis yang lebih dalam: runtuhnya legitimasi moral. Israel, yang kini dikendalikan oleh kelompok sayap kanan ultra-ekstrem, menghadapi kenyataan bahwa impian teokratis mereka tak kunjung terwujud. Sementara rakyat Palestina tetap bertahan di tanah mereka, menolak untuk dikalahkan.
Meski dihantam gelombang bencana yang tampaknya tak berkesudahan, mereka mengirim satu pesan yang tak bisa dibungkam.
“Kami tak akan mengulang Nakba. Kami akan tetap di sini,” kata mereka.
Di hadapan keteguhan seperti itu, Israel tampaknya kehilangan satu-satunya senjata yang tak bisa dibeli: legitimasi moral untuk terus berperang.
*Ahmed Al-Hila adalah seorang penulis dan analis politik Palestina, lahir di Palestina. Ia merupakan tokoh terkemuka di bidang analisis politik, yang memfokuskan tulisannya pada isu-isu Palestina dan Arab, dengan fokus pada isu-isu perlawanan dan hubungan internasional. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Mādzā Ḥadatsa Fī al-Mufāwadzāt? Wa Limādzā Inqalabat Isrāīl?”.