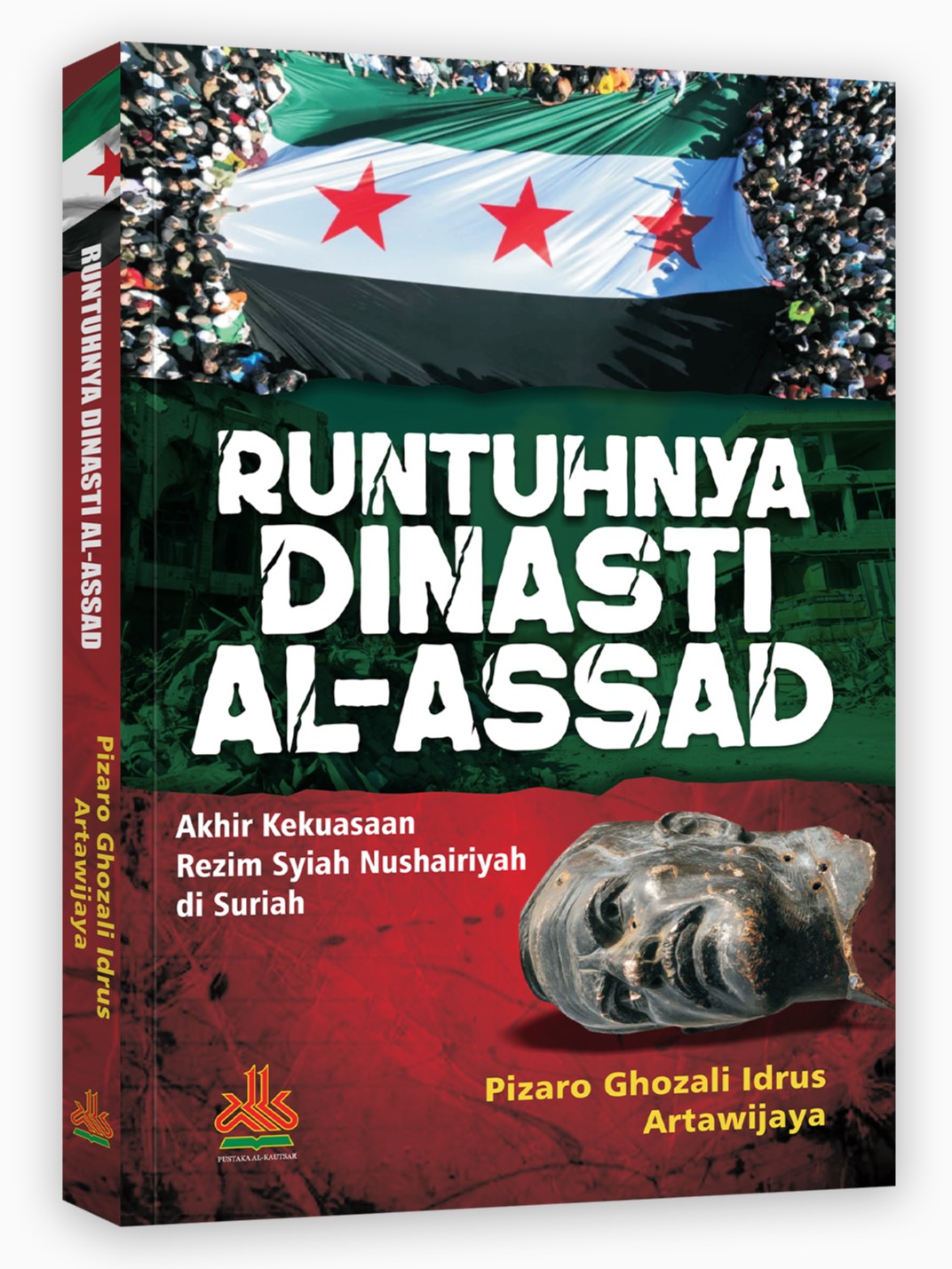Oleh: Ismail Patel
Pernyataan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa lalu bahwa pemerintahnya berniat mengakui Negara Palestina sebelum September sekilas tampak sebagai langkah diplomatik yang penting.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, pernyataan tersebut justru bersifat bersyarat—bukan upaya tulus untuk menegakkan keadilan atau mengakhiri kekejaman yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Alih-alih menjadi tonggak kemajuan, janji pengakuan ini justru berisiko menjadi pengalihan perhatian.
Ia menutupi keterlibatan Inggris dan mengaburkan tanggung jawab historis serta hukum yang selama ini melekat pada negara tersebut.
Di saat warga sipil Gaza mengalami kelaparan akibat blokade yang melumpuhkan, pemerintah Inggris justru menawarkan pengakuan negara Palestina sebagai imbalan bersyarat.
Agresi Israel ke Gaza telah menimbulkan bencana kemanusiaan, dengan lebih dari 60.000 warga Palestina terbunuh sejak Oktober 2023.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menegaskan bahwa kelaparan yang melanda Gaza adalah hasil rekayasa manusia. Genosida sedang terjadi, dan dunia menyaksikannya secara terbuka.
Namun, respons Starmer hanyalah janji pengakuan Palestina—itu pun jika Israel terlebih dahulu memenuhi berbagai prasyarat.
Yaitu, gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, penghentian aneksasi di Tepi Barat, dan lainnya.
Padahal, semua poin itu merupakan kewajiban dasar menurut hukum internasional, bukan kebaikan ekstra dari pihak pendudukan.
Kegagalan moral
Menjadikan pengakuan negara Palestina sebagai sesuatu yang bergantung pada perilaku Israel adalah bentuk kegagalan moral yang serius.
Ini mengirimkan pesan berbahaya bahwa hak dasar bangsa Palestina hanya bisa didapat jika sang penjajah berkenan memberikannya.
Pengakuan bukanlah hadiah atas penghentian kejahatan perang. Penentuan nasib sendiri adalah hak yang tidak dapat dicabut.
Langkah yang sudah terlalu lama tertunda ini, ketika diselimuti syarat-syarat, hanya menjadi penghinaan terhadap martabat rakyat Palestina.
Opini publik di Inggris sudah mencerminkan pandangan ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa 45 persen masyarakat Inggris mendukung pengakuan negara Palestina, sementara hanya 14 persen yang menolak.
Desakan agar pemerintah mengambil sikap lebih tegas terhadap tindakan Israel pun terus meningkat.
Deklarasi Starmer bahwa pengakuan hanya akan diberikan jika Israel mengambil “langkah substansial untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza” bukanlah kebijakan berdasarkan prinsip.
Ia lebih menyerupai manuver politik yang berupaya meredam kemarahan publik, tanpa benar-benar mengkritisi sistem apartheid, pendudukan, dan genosida yang dijalankan Israel.
Membutakan diri terhadap fakta
Sikap Inggris menjadi makin tak dapat dibenarkan jika dilihat dalam konteks hukum internasional.
Pada Januari 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa genosida yang terjadi di Gaza adalah hal yang “masuk akal secara hukum”, dan menyerukan kepada semua negara untuk bertindak mencegahnya.
Kemudian pada Juli 2024, ICJ kembali mengeluarkan opini yang menegaskan bahwa pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal.
Mahkamah juga menyatakan bahwa kebijakan Israel melanggar hukum internasional, termasuk praktik apartheid dan perluasan permukiman yang melanggar hukum.
Namun, meski dua putusan itu sudah sangat jelas, Inggris tetap memasok senjata dan dukungan diplomatik kepada Israel.
Investigasi terbaru mengungkap bahwa sejak September 2024, Inggris telah mengirim 8.630 unit persenjataan ke Israel, termasuk komponen pesawat tempur F-35—setelah sebelumnya menyatakan menangguhkan ekspor senjata.
Anggota parlemen Inggris pun menuding pemerintah telah menyesatkan parlemen dan membahayakan Inggris dengan keterlibatannya dalam kejahatan perang.
Di PBB, Inggris sering kali abstain dalam pemungutan suara untuk mengakhiri pendudukan, dengan alasan perlunya “solusi dua negara melalui negosiasi”.
Namun, mengabaikan kewajiban hukum sambil terus mendukung secara militer dan diplomatik negara yang dituduh melakukan genosida bukanlah netralitas—itu adalah bentuk keterlibatan langsung.
Lebih dari itu, kerangka pengakuan negara yang diusulkan Inggris bahkan tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Menurut hukum internasional, sebuah negara harus memiliki populasi permanen, wilayah yang didefinisikan, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Faktanya, rakyat Palestina kini tercerai-berai: sebagian diblokade di Gaza, sebagian lain hidup di bawah pendudukan militer di Tepi Barat, dan lebih dari 5 juta orang hidup sebagai pengungsi di berbagai kamp di wilayah Timur Tengah.
Wilayah yang hendak diakui sebagai negara Palestina pun terfragmentasi, tidak menyatu, sepenuhnya dikepung, dan dikontrol oleh Israel.
Memberikan pengakuan dalam kondisi seperti ini hanya akan menjadi topeng semu, memberikan ilusi kompromi, sementara kolonisasi terus berlangsung.
Butuh perubahan radikal
Jika Inggris benar-benar serius ingin menegakkan keadilan, pendekatannya harus berubah secara mendasar. Pengakuan bersyarat tidak cukup.
Inggris harus menuntut diakhirinya blokade Gaza secara total dan tanpa syarat. Pemerintah harus mengakui bahwa Israel sedang menjalankan praktik apartheid dan pendudukan illegal.
Selain itu juga menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum internasional, mengakui hak kembali bagi para pengungsi Palestina, dan membebaskan Masjid Al-Aqsha dari kontrol Israel.
Jika tidak, semua yang dilakukan hanyalah bentuk pengalihan dan sikap kompromistis yang menyesatkan.
“Negara Palestina” versi Starmer hanya mencakup 22 persen dari Palestina historis. Tapi, dengan adanya sekitar 700.000 pemukim Yahudi ilegal di 150 permukiman dan 128 pos perbatasan di Tepi Barat.
Wilayah yang benar-benar mungkin diakui bahkan mungkin hanya tinggal 12 persen—dan itu pun masih dibebani dengan syarat-syarat.
Apa yang ditawarkan Starmer pada akhirnya bukanlah pembetulan atas ketidakadilan, melainkan kelanjutannya.
Dari Deklarasi Balfour 1917 hingga hari ini, peran Inggris dalam penderitaan rakyat Palestina tetap berlanjut.
Keadilan tidak datang dengan mengakui serpihan-serpihan hasil penjajahan. Keadilan hanya bisa ditegakkan dengan mengakhiri sistem penindasan yang melahirkannya.
Ini bukan pengakuan negara. Ini hanyalah panggung politik yang menutupi kejahatan terhadap kemanusiaan.
*Ismail Patel adalah penulis buku “The Muslim Problem: From the British Empire to Islamophobia”. Ia juga merupakan Peneliti Tamu di Universitas Leeds dan Ketua LSM Sahabat Al-Aqsha yang berbasis di Inggris. Tulisan ini diambil dari situs Middleeasteye.net dengan judul “Starmer’s dangerous message: Palestinians can only have their basic rights if Israel allows it”.