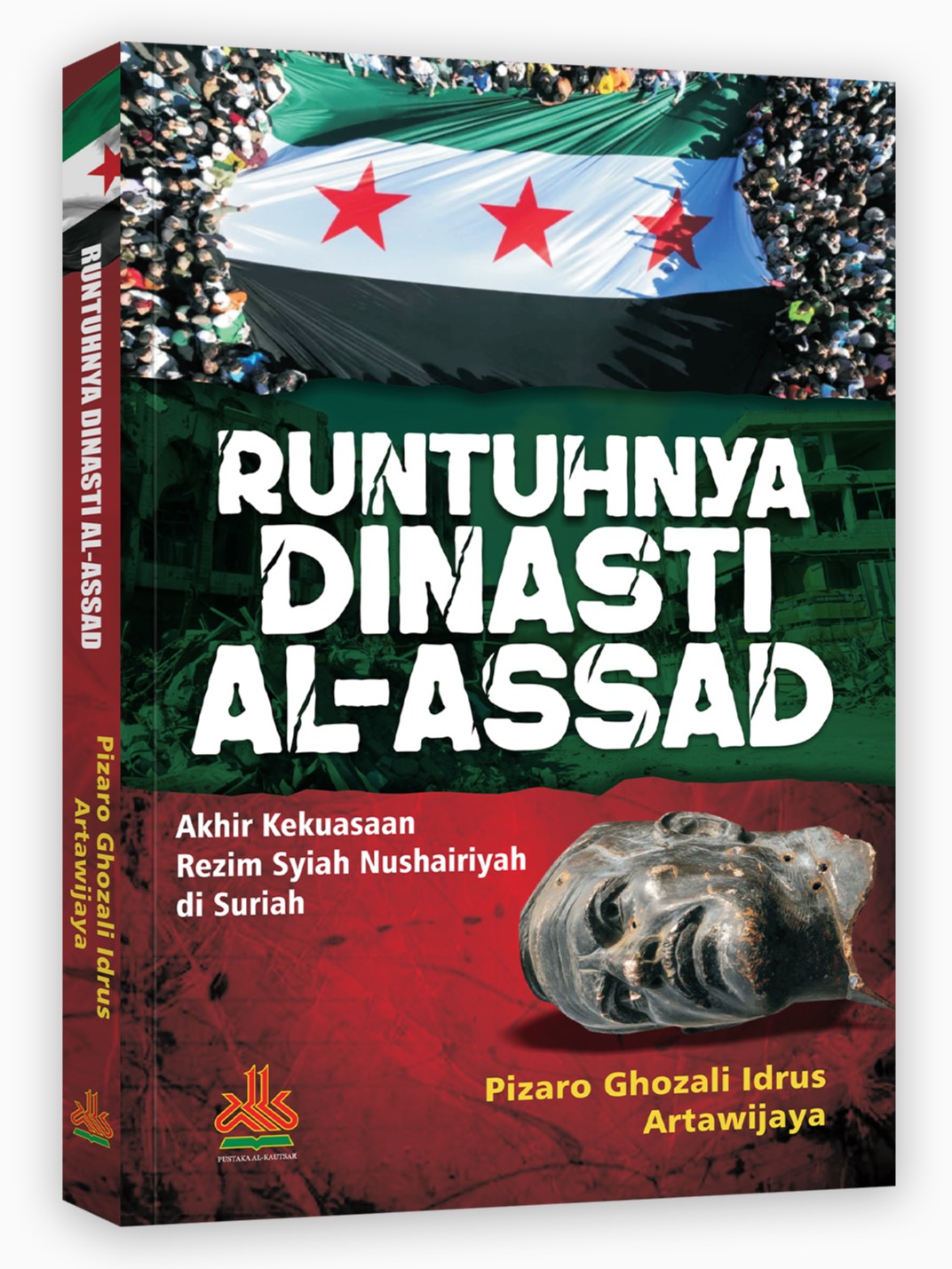Penulis dan analis politik Israel, Aluf Benn, dalam tulisannya di Haartez, menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan datang untuk “merayakan” tercapainya gencatan senjata yang –menurutnya– didayakan oleh tekanan langsung Washington terhadap Israel dan Hamas setelah 2 tahun perang berdarah.
Menurut Benn, Trump ingin menonjolkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih berhasil dari para pendahulunya di Gedung Putih dalam menyelesaikan konflik, padahal sebenarnya tidak ada hal baru dalam pendekatannya.
“Para presiden Amerika sebelumnya pun telah melakukan hal serupa,” tulis Benn, “yakni menahan langkah Israel ketika dianggap terlalu jauh, dan memaksanya untuk menerima penghentian perang.”
Ia menambahkan bahwa kaidahnya sederhana. Bahwa Amerika tidak terlalu peduli ketika Israel merugikan rakyat Palestina.
“Tetapi mereka tidak akan membiarkannya mengganggu kepentingan strategis Amerika di kawasan atau memengaruhi arah kebijakan Washington di Timur Tengah,” katanya.
Begitu Washington menilai bahwa “sekutu kecilnya” telah melampaui batas yang ditentukan, Amerika akan berkata “cukup”, dan para pemimpin Israel terpaksa mundur dari janji-janji besar maupun klaim kemenangan mereka.
Benn mencontohkan beberapa peristiwa sejarah. Pada Perang 1948, Amerika memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya dan menarik pasukan dari wilayah Mesir.
Begitu pula dalam Agresi Tripartit terhadap Mesir pada 1956, ketika Perdana Menteri David Ben-Gurion –yang disebut Benn “melupakan pelajaran sejarah”– memerintahkan pasukannya merebut Semenanjung Sinai.
Di hadapan Knesset, Ben-Gurion berpidato dengan penuh kebanggaan, menyebut operasi itu sebagai kampanye paling agung dalam sejarah bangsa mereka.
“Salah satu yang terbesar dalam sejarah umat manusia,” katanya.
Namun, Presiden AS waktu itu, Dwight Eisenhower, berkoordinasi dengan para pemimpin Uni Soviet.
Selain itu juga memaksa Israel mundur dari Sinai keesokan harinya, disusul kemudian dengan penarikan dari Jalur Gaza.
Menurut Benn, peristiwa seperti itu berulang kali terjadi. “Amerika selalu memegang jam pasir diplomasi dan mereka akan membaliknya sesuai kebutuhan—berdasarkan perhitungan keseimbangan kekuatan serta kepentingan mereka untuk menjaga stabilitas di antara sekutu-sekutu yang berseberangan,” tulisnya.
Benn menilai bahwa Trump kini mengikuti jejak yang sama. Ia memang memberi lampu hijau bagi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu, bahkan turut mendukung operasi itu.
Tetapi ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam euforia keberhasilan militer, berniat melangkah lebih jauh untuk menggulingkan rezim di Teheran, Trump segera memerintahkannya menarik kembali pesawat-pesawat tempur yang sudah terbang membawa amunisi menuju Iran.
“Amerika bersedia melindungi Israel dari ancaman pemusnahan,” tulis Benn, “tetapi mereka tidak akan membiarkan Israel menentukan siapa yang berkuasa di Timur Tengah.”
Di balik pelukan dan pujian
Meski di depan publik Trump dan Netanyahu akan saling berpelukan dan bertukar sanjungan, Benn melihat ada tantangan besar yang membayangi hubungan keduanya: ancaman berakhirnya bantuan militer Amerika untuk Israel.
Menurutnya, Netanyahu sangat menyadari bahwa isu bantuan militer untuk Israel kini menjadi topik beracun di politik Amerika.
Tidak hanya di kalangan Partai Demokrat, tetapi juga semakin banyak dibicarakan oleh politisi Republik.
Tantangan Netanyahu saat ini, kata Benn, adalah bagaimana meyakinkan Washington agar pengurangan bantuan dilakukan secara bertahap, bukan diputus mendadak—terlebih tidak sebelum pemilu Israel berikutnya.
“Dan inilah alasan tambahan mengapa Netanyahu terus berupaya menyenangkan Trump—agar bantuan Amerika tidak hilang sekaligus, dan agar ia tetap bisa memetik keuntungan politik di dalam negeri,” tulis Benn menutup artikelnya.